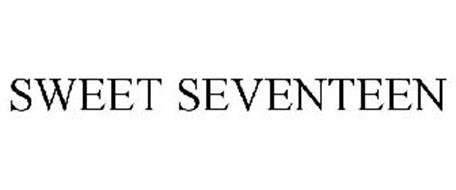Laila
Avignon
Matahari sore menyentuh permukaan kulitku dengan hangatnya. Lambaian angin menyisir pelan rambutku. Aku duduk dengan laptop terbuka di atas kedua pahaku di tempat favoritku; Rocher des Doms. Aku menyapu pandangan ke sekeliling. Pasangan lanjut usia, mungkin sekitar 60 tahun atau lebih, sedang berjalan bergandengan di sebalah baratku menuju ke bangku tempatku duduk. Si Pria yang memakai flannel cokelat muda dan celana bahan warna senada mengapit tangan istrinya dengan tangan satunya terangkat menunjuk ke pepohonan yang berjajar jauh di depan mereka. Melihat itu, tanpa sadar senyumku tersungging.
Aku mengalihkan pandangan ke arah sebaliknya. Seorang wanita 23 tahun terlihat sedang mengabadikan objek dalam memori kameranya. Ia membidik sekumpulan burung yang bertengger di patung perempuan dengan tangan melintang di atas kepala di tengah danau mini taman ini. Ia menurunkan kameranya, melirik padaku dan melontarkan seringai.
Wanita itu berjalan mendekatiku.
“Haven’t done yet?”
Aku menggeleng.
“Udah berapa banyak?” tanyanya lagi.
Aku menatap layar laptop. Terisi setengah halaman.
“Not that much,” jawabku singkat.
Wanita itu bernama Isabel. Seorang fotografer lepas sebuah majalah dan media online berkewarganegaraan Inggris yang menetap di sebelah kanan apartemenku. Usianya yang sebaya menjadikan kami cepat akrab. Ia seorang wanita muda yang cantik. Rambutnya keemasan, hidungnya bangir, pipinya tirus dan jalannya anggun. Meskipun begitu, ia belum menentukan tambatan hatinya, padahal ia bercerita sudah banyak pria yang berusaha mendekatinya. Aku kurang tahu mengapa, mungkin ia belum sepenuhnya membuka diri padaku karena memang kita baru akrab beberapa pekan belakangan.
Isabel duduk disampingku. Ia menyandarkan punggungnya dan mendengus pelan. “Terlalu banyak pikiran, Laila?”
Aku mengangguk pelan sembari tersenyum risau.
Aku masih menulis untuk beberapa media online dengan menggunakan nama penaku; Laura Michelle. Karena menulis menjadi alasan bagiku untuk menjalani hari-hariku di kota ini yang semakin lama semakin menjemukan. Bukan, bukan karena kebahagiaan di kota ini mudah menguap, melainkan karena hampir seluruh bagian hatiku tertinggal di Indonesia, pada seorang lelaki pemimpi bernama Andre.
Beruntung aku mengenal Isabel. Mas Fahri tidak pernah menceritakan padaku perihal tetangga kami satu ini karena memang mereka jarang berpapasan, dan jikapun begitu mereka hanya saling menegur sekenanya.
Pertama kali aku bertemu dengannya kala aku baru pulang dari Galerie Ducastel tak jauh dari apartemenku. Saat itu aku mendapati seorang wanita yang nampak kebingungan di depan pintu kamar sebelah kanan kamarku. Ia berjalan mondar-mandir dengan satu tangan memegang keningnya, menandakan ia cukup jangar.
Ketika aku berada tepat di depan pintu, ia menilikku.
“Kamu tinggal di situ?” adalah kalimat pertama yang ia lontarkan. Aku segera menyimpulkan bahwa ia seorang Britania, terdengar dari aksennya yang begitu kental.
“Iya,” jawabku singkat.
“Bukannya di situ tempat tinggal Fahri?” Ia bersandar menghadapku pada tembok diantara kamar kami.
“Ya, saya istrinya,” ucapku dengan berat hati.
“Oh,” balasnya singkat sambil memerhatikanku dari atas ke bawah. Aku mafhum, Mas Fahri pernah cerita kalau Florencia sempat tinggal di sini. Jadi wanita ini keheranan karena aku yang mengaku sebagai istri Mas Fahri begitu berbeda dari yang biasa ia lihat.
“I know what you thinking. Aku bukan dia yang sempat kamu lihat sebelumnya,” jelasku.
“Okay, sorry then. I’m Isabel by the way.” Ia mengulurkan tangannya.
“Laila,” aku menyambut uluran tangannya. “Apa yang mengganggumu, Isabel? Kamu nampak pusing aku perhatikan,” lanjutku.
Ia menepuk dahinya. “Ah, iya! Aku kehilangan kunci kamarku ketika perjalanan pulang tadi. Dan kunci cadangan ada di lemari kamarku, sekarang aku bingung bagaimana caranya masuk.” Dia diam sejenak. “Ah! Benar! Untung ada kau, apakah kau punya kawat?”
Aku mengangkat kedua bahuku. “Entahlah, tapi mungkin ada.”
“Can you bring me some?” Aku mengangguk dan berlalu memasuki kamar.
“Mungkin ada di dapur,” desisku pelan. Setelah mencari di berbagai counter, akhirnya aku menemukan kawat sepanjang, entahlah, mungkin setengah meter. Segera aku bawa kawat itu keluar.
Wajah Isabel sumringah kala aku membawakan kawat yang ia cari. Ia lalu membuat meminta gunting dan memotong seperempat dari panjang kawat. Kemudian ia tekuk kawat pada titik tengahnya hingga membentuk huruf U. Setelah itu ia memasukan kawat ke dalam lubang kunci dan melakukan sedikit ‘sulap’ hingga beberapa saat kemudian bunyi ‘krek’ terdengar dari pintu.
Isabel tersenyum puas ketika apa yang ia kerjakan berhasil. Aku yang sedari tadi menjadi penonton hanya terpana melihat ‘perampokan’ terhadap apartemen sendiri ini.
Semenjak saat itu kami yang pada awalnya jarang bersitatap menjadi hampir tiap hari menghabiskan waktu bersaama dan pada beberapa kesempatan Mas Fahri mengajak Isabel untuk makan malam bersama di apartemen kami.
Kembali ke Rocher des Domes, aku mengerling ke arah Isabel yang kini duduk di tempat kosong di sebelahku. “Kau sudah selesai dengan aktifitas fotomu?”
“Untuk sekarang, sudah. Mau lihat?” Isabel mencondongkan badannya ke arahku. Aku melihat seksama display kameranya. Ia menekan tombol next untuk memperlihatkan beberapa foto yang ia tangkap.
“Bagus seperti biasa, matamu sangat jeli menilai objek mana yang pantas untuk diabadikan.”
“Ah, tidak juga, Laila. Menurutku, semua orang bisa menjadi fotografer. Sama sepertimu, semua orang bisa menjadi penulis. Ini hanya masalah jam terbang, bahkan ada beberapa orang yang ditakdirkan dengan bakat fotografi,” jelasnya.
“Bagaimana sekarang? Kau masih ingin di sini atau kita pergi ke tempat lain?” tanya Isabel.
“Aku rasa duduk di sini untuk beberapa menit ke depan bukan ide yang buruk. Hey! Bagaimana kalau kita memberi makan burung-burung itu?” Aku menunjuk kumpulan burung dara yang sedang mengais makanan di jalan tak jauh dari tempat kami duduk. Isabel hanya mengangguk dan bergerak mengikutiku.
“Isabel,” aku memanggilnya tanpa mengindahkan pandangan dari kumpulan burung yang kini berada tepat di sekitar kakiku.
“Ya?”
“Apakah kau pernah tinggal bersama orang yang tidak kau cintai?” entah mengapa aku menelurkan kalimat itu.
Tidak ada jawaban selama beberapa saat. “Itukah yang sedang kamu rasakan, Laila?” Isabel menjawab pertanyaanku dengan pertanyaan. Aku terdiam. Gerakan tanganku yang sedari tadi menebar makanan ringan ke kawanan burung ikut tertahan.
“Aku tidak tahu sampai kapan ini akan berakhir,” jawabku lemah.
“Mungkin sebaiknya kita ke Le Cid Cafe. Aku rasa di sini bukan tempat yang cocok untuk membicarakan perkara ini, Laila.”
Aku mengiyakan dan kami berlalu menuju tempat yang telah di tentukan. Sebuah kafe kecil di dekat apartemen kami, namun ramai oleh pengunjung setiap harinya dikarenakan arus manusia yang melalui Rue de Republique tak pernah lenggang.
Kami duduk di bagian luar kafe yang langsung menghadap ke Jalan Republik karena di dalam sudah tidak memungkinkan tersedia tempat kosong. Isabel memesan andromaque, salad dengan potongan daging ayam dan disajikan ala Thailand. Sedangkan aku hanya memesan cappuccino.
“Aku rasa aku mengerti masalahmu,” Isabel membuka percakapan. “Setidaknya itu yang sempat aku pikirkan kala pertama kali melihatmu di kamar sebelah. Kamu bukan wanita yang kemarin sempat tinggal di sana.” Tukasnya.
“Aku tahu kau berpikiran begitu. Tapi, apakah kamu mengenalnya?”
“Tidak begitu, ia jarang bersosialisasi. Bahkan dibanding dengan Fahri yang sudah terhitung jarang bertemu denganku, wanita itu masih di bawahnya.” Isabel berbicara sembari menyantap saladnya.
“Sifatnya sangat berbeda darimu, Laila. Entahlah,mungkin karena kalian orang Indonesia yang pernah kudengar peringainya ramah dan hangat hingga terbuka bagi siapapun. Sebenarnya aku pun mempunyai sifat yang sama seperti wanita itu, tapi berbicara denganmu membuatku tak acuhkan sisi lainku yang satu itu.” Aku tersenyum mendengar penjelasannya.
“Oh ya, tentang pertanyaanmu di Rocher des Doms tadi, aku tidak pernah mengalami seperti apa yang kamu alami sekarang, tapi aku tau rasanya ditinggal pergi oleh orang yang sangat kucintai.”
Aku menaikkan satu alis. “Dia meninggalkanmu seperti....memilih bersama perempuan lain?”
Isabel terkekeh sampai makanan di mulutnya hampir keluar. Ia mengambil tisu untuk membersihkan daerah mulutnya sebelum menanggapi ucapanku. “Tidak, bukan begitu.”
“Lalu?” aku semakin penasaran dibuatnya.
Ekspresi Isabel berubah seketika. Kini nampak kemurungan yang kentara terhias diwajahnya. “Dia meninggalkanku selamanya. Kecelakaan tunggal 2 tahun lalu di London.”
“Eh? Maaf kalau begitu, tidak seharusnya aku bertanya,” kataku merasa tak enak.
“It’s okey, Laila,” ia tersenyum getir padaku. “Anyway, life must go on, right?” hanya dalam beberapa detik ia mampu mengubah raut wajahnya seperti sedia kala kembali.
“Aku tarik dari kata-katamu tadi, berarti sekarang kamu tinggal dengan orang yang tidak kamu cintai dan ada seseorang yang kamu cintai nun jauh di sana yang kamu tinggalkan?”
Aku terkesiap menangkap kalimatnya. Isabel cukup melihat mimik keterkejutanku untuk memastikan tebakannya tidak salah.
“Boleh aku memberi saran, Laila?”
Aku mengangguk.
“Aku memang tak tahu bagaimana kamu bisa sampai ke titik ini. Aku hanya ingin mengatakan, jangan terlalu lama mendustakan isi hatimu sendiri. Segera pulang ke tempa dimana kau semestinya, sebelum semua terlambat. Sebelum orang yang memang kamu cintai hanya bisa didatangi di pemakaman setempat,” Isabel menjeda kalimatnya. “Aku tahu, tempat ini cukup bagus untuk ragamu, tapi tidak bagi hatimu. Dan sampai saat itu tiba, saat dimana kamu akan kembali ke pelukan sesungguhnya, aku ada 2 meter di samping kamarmu.” Ia menutup perkataannya dengan sebuah senyuman.
---
Ada beberapa aturan yang aku dan Mas Fahri setujui bersama. 1). Hubungan ini didasari oleh keinginan orang tua kita, jadi jangan menggunakan hati di dalamnya. 2). Tidak ada singgungan tentang anak dalam hubungan ini. Meskipun aku tetap melayaninya karena bagaimana pun juga ia merupakan suami sahku.
Hubungan kami memang terkesan seperti antara abang dan adiknya, meskipun itu tak berlaku kala kami bergumul di ranjang beberapa kali. Namun, suatu ketika, kala hubungan ini berjalan lebih dari setahun, aku menangkap gelagat berbeda ditujukan Mas Fahri.
Aku paham aku tak sebodoh itu, aku paham kalau ia berusaha membawa hubungan ini ke arah yang semestinya; suami istri sesungguhnya. Bahkan dalam beberapa kesempatan ia turut memasukkan ‘anak’ dalam topik pembicaraan kami, juga ia mulai menjadi protektif dan menguarkan perhatian lebih.
Aku tahu itu bukanlah sesuatu yang salah dalam hubungan suami istri, tetapi tidak pada hubungan ini.
Saat dimana hal-hal demikian itu mulai terlihat adalah ketika aku menyambangi Paris untuk pertama kalinya. Aku berpikir, sekarang aku berada di salah satu destinasi favorit di Eropa, mengapa aku tak mengunjungi Eiffel tuk pertama kali selagi kesempatan ini ada?
Aku memang biasa pergi keliling Avignon tanpa mengabari Mas Fahri terlebih dahulu, terlebih aku selalu kembali ke apartemen sebelum Mas Fahri pulang kerja. Aku tahu, tidak seharusnya seorang istri bepergian tanpa sepengetahuan dan seizin suaminya. Tapi untuk kasus satu ini, aku bahkan meragukan status istri yang kusandang sendiri.
Maka, pada hari itu aku putuskan pergi ke Paris seorang diri. Isabel berhalangan mendampingiku karena ada urusan pekerjaan di Bordeaux.
Perjalanan dari Avignon menuju Paris ditempuh dalam waktu 3 jam dengan TGV. Bermodal peta dan rekomendasi tempat yang aku dapatkan dari internet, membuatku merasa pede dalam kenekatanku untuk berkeliling Paris.
And here i am. Paris dengan segala keelokannya. Aku nampak berseri kala menginjakkan kaki pertama kali di Kota Cahaya ini. Mataku menyapu sekeliling, memerhatikan bagaimana wajah Parisian atau penduduk paris yang sangat khas. Dagunya, raut mukanya, hidungnya, seakan Paris bukan hanya elok dari segi aristekturnya, melainkan juga dari penduduknya.
Berhubung aku sampai pada waktu hampir tengah hari, aku langsung menuju destinasi utamaku, sebuah sutet yang dibanggakan warga Paris, Eiffel Tower. Aura romantis langsung menguar setiba aku di sana. Aku mengabadikan beberapa foto dalam pocket camera yang aku pinjam dari Isabel; muda mudi yang berciuman tak jauh dari tempatku berdiri, lalu ada pasangan yang asyik bercanda sambil tak henti menunjuk menara eksotis itu. Aku tersenyum melihat mereka. Dan dalam hati kecilku, aku pun ingin berada di posisi mereka, dengan Andre tentunya.
Sebetulnya Eiffel akan ramai menjelang malam hari, karena orang-orang dapat melihat pemandangan Paris yang gemerlap dari puncak Eiffel. Namun, karena waktuku yang terbatas, maka aku mengantri tiket Eiffel pada siang hari. Biarlah, setidaknya rasa penasaranku terbunuh dengan ini. Toh, berada di puncak Eiffel saja udah lebih dari cukup bagiku.
Aku hanya punya sedikit waktu di sini, sehubungan dengan telah terpuaskan rasa penasaranku dengan menara Eiffel, maka selanjutnya kuputuskan membawa kakiku ke Saint-Pierre de Montmarte, salah satu gereja tertua di Paris yang terbuka untuk umum dan turis. Letaknya yang berada diketinggian membuat siapapun yang berdiri di sana dapat melihat Paris dari atas dan itu sangat sangat luar biasa indahnya. Seakan ada sensasi berbeda yang diberikan apabila melihat Paris dari ketinggian di sini dan dari puncak Eiffel. Dan beruntung, di sekitar Montmarte ada Flea Market atau pasar loak yang menyediakan begitu banyak barang mulai dari jam hingga ornamen khas Prancis. Riuhnya pasar loak tersebut juga kuabadikan dalam lensa kamera milik pinjaman ini.
Aku sudah memesan tiket pulang berupa penerbangan paling malam dari Paris ke Lyon yang kemudian dilanjutkan naik TVG ke Avignon. Sengaja kulakukan karena aku ingin mengeksplore Paris lebih lama. Meskipun hanya dua landmark Paris yang bisa kukunjungi, tapi aku cukup puas telah melihat keanggunan Paris dari tiap kelok jalanannya, orang-orangnya dan bangunannya.
Hingga saat aku sedang menunggu waktu boarding-ku dengan menghabiskan makanan di salah satu restoran cepat saji asal Amerika, ponselku berdering. Mas Fahri.
“Laila, kamu dimana?” tanyanya dengan suara terburu-buru.
“Paris,” kataku singkat.
“PARIS?!” ia menyentak. Membuatku harus menjauhkan ponsel dari telingaku. “Ngapain kamu ke sana?!”
“Iseng, liat Eiffel, terus pulang.”
Mas Fahri menggeram sesaat. “Laila! Pulang sekarang! Kenapa nggak bilang sih kalau kamu ke Paris?!”
Aku mengrenyitkan dahi. Tak biasanya ia semarah ini kalau aku bepergian sendirian. Memang sebelumnya aku biasa sampai sebelum Mas Fahri pulang, tetapi toh ini baru pertama kali aku begini. Dan ini pertama kali Mas Fahri marah dengan kelakuanku.
Akan tetapi di situ aku merasakannya.
Mas Fahri berbuat begitu karena ia takut aku mengalami kejadian tidak mengenakkan. Terlebih aku orang asing yang hanya mengandalkan jalanan Paris dari smartphone miliknya. Aku tahu, ada hal lebih yang ingin diperjuangkan Mas Fahri. Dan itu berusaha aku tampik.
Aku sampai di apartemen setelah hampir 12 jam berada di luar. Setelah menaruh jaketku di holder dekat pintu, aku mendapati pemandangan yang membuat hatiku meringis.
Mas Fahri tidur telengkup di sofa depan TV masih lengkap dengan pakaian kerjanya. Aku tahu ia menungguku pulang hingga tertidur.
Dan saat itu pula pertama kali aku menaruh perhatian padanya.
to be continued