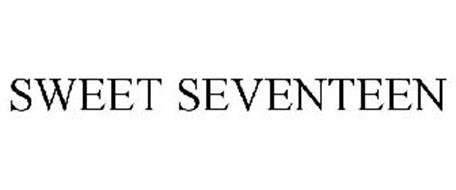Laila
Avignon, awal musim gugur 2016.
Saat-saat paling membahagiakan di
Avignon telah berlalu, musim panas telah berakhir dan digantikan musim gugur
dengan semilir anginnya yang menyejukkan. Kebahagiaan musim panas di Avignon
membuat seluruh sudut kota ini menjadi hidup. Terkhusus Rocher des Doms, taman itu hampir tak pernah sepi tiap harinya
sehingga membuatku yang kerap duduk sendirian di bangku taman favoritku tak
pernah benar-benar merasa sendiri.
Because i need to be alone, but not to be lonely.
Mungkin hanya aku dari lebih dari
90 ribu penduduk Avignon yang melewati musim panas dengan raut wajah—bagaimana
ya aku mengatakannya? Ah, menyedihkan.
Sekitar dua bulan lalu, Mbak Aya
memberi kabar bahwa kondisi Ibu kritis. Kabar itu menjadi pukulan telak bagiku
yang berada ribuan kilometer jauhnya dari rumah. Kala itu Mas Fahri sedang ada
banyak tanggungan pekerjaan dan mengatakan bahwa aku saja yang pulang ke Indonesia,
sedangkan Mbak Aya telah lebih dahulu berada di Jakarta untuk menjaga Ibu.
Kurang dari dua minggu aku berada
di Jakarta, menemani dan merawat Ibu setiap hari, namun aku tidak bisa berbuat
apa-apa kala Yang Memberikan Nyawa telah mencabut apa yang telah Ia tiupkan
pada makhkuknya. Detik itu pula waktu dan putaran bumi serasa terhenti. Sosok
malaikat yang menjaga, merawat hingga membesarkan aku serta Mbak Aya telah
meninggalkan kami untuk selamanya. Mas Fahri segera menyusul ke Indonesia
ketika aku memberitahu kabar duka ini.
Mbak Aya menyuruhku kembali ke
Avignon setelah masa cuti yang diambil Mas Fahri habis. Aku menolak untuk
berangkat dan mengatakan ingin kembali tinggal di rumah selepas Ibu pergi. Mas
Fahri yang mendengar aku menolak ke Avignon nampak murung, namun ia tak banyak
bicara mengenai keputusanku itu.
Pasca cekcok cukup lama dengan Mbak
Aya, akhirnya aku (terpaksa) mengikuti sarannya dengan keputusan akhir Mbak Aya
akan tinggal di rumah setidaknya sampai 40 harian Ibu dan untuk selanjutnya ia
akan kembali ke Jepang dan rencananya rumah akan dikontrakan untuk sementara
waktu. Mbak Aya juga mengatakan selama di Indonesia ia akan mencari calon
penyewa rumah yang tepat karena ia tak ingin sembarangan orang mengisi rumah
keluarga ini.
And here it goes, berada di balkon apartemen kecil ini dengan ginger
tea dalam genggaman. Menikmati angin musim gugur yang menyeka rambutku lembut
dan melihat orang-orang yang bergerak dinamis di Rue Viala.
Oh ya, berbicara mengenai
hubunganku dengan Mas Fahri, sebelum kabar tentang Ibu menghampiri, Mas Fahri
tampak semakin berusaha menjadi suami seutuhnya dan ia benar-benar mengusahakan
kami menjadi pasangan suami-istri selayaknya.
Mungkin semua itu nampak normal dan
justru terdengar baik bagi orang luar. Tapi bagiku, keadaan ini malah semakin
terasa memburuk. Semakin dalam perasaan Mas Fahri yang kurasakan, maka akan
semakin sulit pula hubungan ini untuk diselesaikan. Begitulah sekiranya.
Setelah berpulangnya Ibu ke hadapan
Allah, pikiranku berkecamuk mengenai hal-hal lain yang berkaitan tentang Ibu
dan pernikahanku. Bagaimana aku dan Mas Fahri bisa bersatu hingga kini, dan
sekarang bagaimana aku menyudahi hubungan ini karena Mas Fahri dirasa telah
benar-benar mencintaiku.
Sepulang dari Paris, setelah ia
bangun dari tidurnya di sofa dan mendapati tubuhnya ditutupi selimut, ia
berpikir bahwa aku telah memiliki rasa perhatian selayaknya seorang istri pada
umumnya.
Ya, memang aku mulai menaruh
perhatian padanya saat itu.
Tapi,
Bukan berarti perhatianku bisa
disamakan seperti perhatian seorang istri pada suaminya. Perhatianku hanya
sebatas menghargai orang yang juga punya perhatian terhadapku.
Maybe what i’ve done sounds like an evil for everybody, but that’s the
truth.
“Jangan lagi-lagi coba kayak apa
yang kamu lakukan kemarin,” ucapnya kepadaku dengan nada yang menenangkan.
‘Shit. Don’t do this,’ pikirku.
Selepas itu, ada satu kebiasaan
baru yang ia ciptakan yang sempat membuatku canggung ketika pertama kali
diterapkan—bahkan hingga kini, yaitu setiap ingin berangkat dan saat pulang
dari kantor, ia mencium keningku. Sekali lagi, sebenarnya ini wajar bagi suami
istri dimanapun itu, tapi sekali lagi pula aku katakan, ini sudah terlalu jauh
buatku.
Hingga pada suatu sore di akhir
pekan aku duduk berdua dengan Isabel di sebuah kedai kopi kecil di Rue Vieux Sextier—tak jauh dari apartemen
kami. Aku memesan hot chocolate dan souffle au chorizo, sedangkan Isabel
sedang menyeruput chocopom d’amour
mereka yang lezat.
Pada titik ini, aku merasa butuh
seorang teman untuk mencurahkan isi pikiranku. Hey, aku tak setegar itu dalam
memendam perasaan. Sebenarnya aku lebih memilih Nadine sebagai pendengarku
untuk perkara ini, namun perbedaan waktu yang cukup ketara dirasa mengganggu
menentukan kapan saat yang tepat untuk berbagi.
“Isabel,” sahutku sembari memutar
sendok dalam cangkir di hadapanku tanpa melihat ke arahnya.
“Ya, Laila?”
“Jika kau berada di posisiku, apa
yang akan kau lakukan?”
Isabel berdehem sebentar.
“Aku tak tahu, Laila. Setiap orang
punya masalahnya sendiri untuk dihadapi. Dan kemampuan tiap orang dalam
menghadapi masalah itu berbeda-beda. Mungkin aku bisa melewati masalahmu dengan
mudah, atau bahkan aku tak mampu bertahan melebihi yang kau lakukan sekarang,
karena aku tak tahu bagaimana rasanya, Laila.” Aku berhenti memainkan sendok,
namun bola mataku masih tertanam pada souffle
au chorizo yang sedari tadi belum kusentuh.
“Coba kau lihat pasangan di luar
sana,” Isabel menunjuk ke arah kaca besar di belakangku. Aku sedikit memutar
badan, lalu mendapati seorang pria dengan polo
shirt hitam memandang sayu wanita cantik dengan dress putih di depannya. Wanita itu menatap cangkir yang telah
kosong di tangannya. “Si wanita merasa sedih karena memergoki si pria yang
ketahuan selingkuh untuk kali ketiga. Sedangkan si pria mencoba mengklarifikasi
dan meyakinkan bahwa hal itu nggak akan terjadi lagi,” terusnya.
Aku melayangkan tatapan ragu pada
Isabel. Ia hanya tersenyum.
“Lalu yang di sana itu.” Kali ini
ia menunjuk seorang pria berkacamata dengan rambut di kuncir kuda yang tengah
menatap layar laptop dengan menopang dagu menggunakan punggung tangannya.
Aku mengangguk, ia melanjutkan. “Ia
seorang penulis di sebuah media lokal yang tengah dikejar deadline namun tak tahu apa yang harus ia tulis karena dalam
pikirannya berkecamuk banyak hal, termasuk, ‘mengapa
aku memilih kedai ini? Ah, sisa uangku untuk hari ini habis hanya untuk membeli
minuman macam ini.’”
“I hear what you say, lady,” ujar pria yang sedang dibicarakan
Isabel. Aku membelalak sembari menahan tawa pada Isabel. Aku melihat pemilik
kedai menggelengkan kepala. Isabel meminta maaf sambil tergelak dari tempatnya
duduk.
“Sudahlah, ilmu cenayangmu makin
lama makin keterlaluan,” kataku.
“But, there’s one thing that i see from you, Laila,” aku
mengangkat dagu. “You’re on of the
strongest girl that i’ve ever met. I believe you can handle this. I believe
that you can through all of that shit.” Isabel tertawa, dan senyum
pertamaku hari itu tersungging.
“Just follow your heart, Laila,” Ia melanjutkan. “Meskipun
beberapa kali logikamu mengatakan, ‘ah,
kamu jahat,’ atau, ‘yang akan kamu
lakukan itu kejam, tak berperasaan.’
Biarlah, jangan didengar. Anggap saja
bahwa logikamu itu bagai sebuah lautan, kamu seorang nahkoda kapal dan hatimu
adalah dermaga tujuanmu. Kemana pun lautan mencoba membawa kapalmu, tapi
pahamilah kalau kamu mampu mengatasi itu karena kamu sejatinya tahu kemana
tujuanmu sesungguhnya.”
Aku tersenyum.
“One more thing, Laila, and it’s very very important to hear.” Aku
menaikkan sebelah alisku, memposisikan kedua tanganku di atas meja dan sedikit
mencondongkan badanku ke arahnya.
“Kalau kamu nggak mau memakan souffle au chorizo itu, sebaiknya buat
aku saja,” katanya sambil menahan tawa. Rasanya kuingin melempar sendok kecil
ini ke arahnya saat itu.
---
Kembali ke kondisi saat ini, dimana
suasana sore Avignon yang menenangkan membawa pikiranku melayang ke belasan
tahun lalu. Dimana kali pertama aku diajak Ayah dan Ibu pergi ke Kebun Binatang
Ragunan, bersama dengan Mbak Aya juga
tentunya.
Usiaku yang begitu belia dan penuh
dengan pertanyaan membuatku menjadi bocah yang cerewet.
“Bu, itu apa?” Kataku menunjuk
salah satu kandang.
“Itu singa, Laila,” balas Ibu.
“Lalu, itu apa?”
“Itu simpanse, Laila,” Ibu selalu
membalas tiap pertanyaanku dengan senyuman.
“Kenapa dia bisa jalan kayak
manusia, Bu?”
“Anak Ayah ini banyak tanya, ya.
Kelak kamu jadi manusia yang cerdas,
Nak,” potong Ayah sebelum Ibu menjawab pertanyaanku. “Kamu mau es krim,
Laila?” Tawar Ayah. Aku girang bukan kepalang mendengarnya.
Aku berpikir, kebahagiaan itu akan
bertahan selamanya. Namun semua itu hanya titipan yang bersifat sementara.
Kebahagiaan itu bisa berakhir kapan saja.
“Hey,” suara berat itu
menyadarkanku, lalu sebuah tangan melingkari pinggangku dari arah belakang. Mas
Fahri.
‘Oh crap, not again,’ balasku dalam hati.
“Hey, Mas,” aku meliuk sejenak,
mencoba melepaskan diri dari pelukannya. “Tumben pulang cepat?” Lanjutku
setelah terbebas dari sergapannya.
“Kangen istri,” ucapnya tersenyum.
“Yeee ditanya serius juga, malah
gombal.”
Mas Fahri kemudian memegang pagar
balkon apartemen, menegakkan punggungnya dan menghirup nafas dalam. “Emangnya
nggak boleh ngegombalin istri sendiri?” Jawabnya melirik padaku.
‘Enggak boleh, Mas, nanti perasaan ini bisa terlalu jauh. Hati ini masih
punya Andre walau sekeras apapun kamu mencoba merebutnya, Mas.’
“Yaaa....boleh sih,” balasku ragu.
Keheningan menyeruak diantara kami
selama beberapa saat, sebelum ia kembali bersua.
“La?”
“Ya, Mas?”
“Aku terkadang ngebayangin deh, di
sore hari gini, aku dan kamu menikmati hari di balkon ini sembari salah satu
diantara kita merangkul si kecil.”
Aku terperanjat sejenak, melihat ia
yang kini memandang luas ke arah langit.
Itu merupakan yang keempat untuk
minggu ini dirinya menyinggung masalah buah hati. Intensitasnya berbicara
seperti itu semakin meningkat dari waktu ke waktu. Padahal pada awal
terciptanya hubungan ini, kami setuju untuk menyingkirkan pembahasan mengenai anak
karena kami sadar hubungan ini tak akan bertahan selamanya.
Dan dengan adanya anak, maka cincin
di jari manis ini akan terpasang lebih lama.
Memang, banyak pasangan yang
mengakhiri status pernikahan mereka walaupun telah memiliki buah hati, namun
aku tak bisa melakukan hal serupa. Aku, tak mau mengorbankan anak yang tak
berdosa dan tak tahu masalah sesungguhnya dibalik perpisahan orang tuanya.
Aku tak mau, dan tak bisa.
“Kalau menurutmu, bagaimana, La?”
Tanyanya lagi, ku merasakan pandangannya berganti padaku, namun mataku tertuju
pada kedua kakiku.
Mulutku masih terbelenggu. Aku tak
ingin menjawabnya.
“La?”
Sial, dia memaksa.
“Iya, Mas?”
“Kamu ada di sini, kan?”
“Ha? Maksudnya? Iyalah, Mas, aku di
sini,” sergahku.
“Bukan, maksudku pikiranmu, La.”
‘Kau ingin jawaban jujur atau jawaban yang memuaskanmu, Mas?’
“Iya, Mas, aku di sini, kok,”
jawabku.
“Lalu, gimana menurutmu, La?”
Aku menatapnya kini. “Tentang
anak?”
Dia mengangguk.
“Entahlah, Mas,” kataku lirih.
Kembali terjadi keheningan. Aku
tahu Mas Fahri menunggu jawaban utuhku, maka aku lanjutkan. “Aku nggak tahu
apakah dengan adanya anak bisa menyelamatkan pernikahan kita. Aku juga nggak
tahu mengapa sekarang kau sangat sering menyinggung permasalahan ini, padahal
ide tak adanya anak kau sendiri yang menyuarakan di awal hubungan ini, Mas.”
Aku merasa tak berani menatapnya
lagi setelah mengatakan itu. Sebelumnya, acap kali Mas Fahri mencoba membahas
persoalan ini, aku selalu bersikap acuh tak acuh atau mengalihkan pembicaraan
ke topik lain. Namun, kali ini aku mengatakannya dengan lantang, suara hatiku
yang terpendam selama ini.
“Kenapa, La?” Firasatku mengatakan
tak enak tentang ini. “Kenapa? Kita, udah satu tahun, La, kenapa seakan ini
semua tak ada artinya bagimu?”
I wish i can go away from here now.
“Kita ada di satu atap yang sama
setiap harinya. Bangun dan ingin tidur yang pertama kali aku lihat adalah kamu.
Setiap aku pulang kerja, kamu orang yang ada untuk menyambut aku, begitupun
ketika aku berangkat, kamu orang yang mengantarku sampai ke depan pintu dan
melihat punggungku semakin menjauh sampai mata tak mampu menjangkaunya lagi.”
Ia diam. Aku semakin erat menggenggam cangkir di tanganku.
“Beberapa kali kita
pergi ke berabagai tempat di Prancis, sewaktu aku ajak kamu ke Marseille untuk
melihat kantorku, atau ketika kita keliling Paris bersama. Apa itu tak ada
artinya bagimu? Apa semua keceriaanmu hanya fana belaka?”
Suaranya kian memberat.
“Hentikan, Mas.”
“Kenapa, La? Kenapa kamu bisa
bersikap seakan tak ada apa-apa diantara kita?”
‘Memang tak ada apa-apa, Mas, dari dulu tetap dan akan selalu begitu.’
“La, aku mau jujur soal
perasaanku,” katanya lagi dengan suara semakin lirih.
‘Mas, hentikan, aku nggak mau dengar.’
“La, pada awalnya aku memang
menganggap hubungan ini sebatas formalitas belaka demi membuat tenang hati
kedua orang tua kita, terutama almarhum Ibumu. Namun, hari demi hari dilalui
bersama dengan hanya satu orang membuat hati ini tergerak juga untuk membawa
hubungan ini ke jalan yang seharusnya. La, aku percaya bahwa cinta datang
dengan berbagai cara, salah satunya ialah cinta bisa datang karena terbiasa.”
‘Tapi aku bukan tipe orang yang bisa cinta karena terbiasa, Mas.’
Bibirku masih terkatup.
“La, aku telah meninggalkan semua
peristiwa masa lalu dan bersiap menghadapi masa depan yang terlihat nyata di
depanku kini. Aku tak pernah berbicara mengenai ini sebelumnya karena aku pun
melihat kamu merasakan hal yang sama, La, tapi kelihatannya kamu tidak
terpengaruh itu semua.” Desau angin berhembus menyapu kulit tipisku dan
membelai rambutku. Aku sama sekali tak berkeinginan untuk membalasnya, mencoba
tidak menggores hatinya sekecil apapun.
“La, lalu apa arti kebahagiaan itu?
Kebahagiaan yang kerap terpancar dari wajahmu? Sorot mata yang berbinar acap
kali aku menggenggam tanganmu? Apa arti semua itu, La? Apakah itu karena aku,
atau hanya murni karena kamu terpana dengan indahnya Prancis?”
“Mas, hentikan....”
“Apa hidup dengan memakai topeng
seperti itu selama ini terasa nyaman bagimu?”
Aku sudah tak tahan lagi mendengarnya.
“MAS!”
Ia tersentak, nampak tak percaya
dengan reaksiku.
“Aku bilang sedari tadi untuk
hentikan omongan ini. Aku nggak bisa, Mas, aku nggak bisa,” aku berusaha
menatapnya yang masih tergambar perasaan shock
di sana. “Aku berusaha untuk tak mengatakan apapun karena....aku takut....takut
melukai hatimu, Mas.”
“Tapi, diam mu cukup menciderai
hatiku, La, meskipun kecil. Dan, dengan begini kamu tetap akan meninggalkanku,
bukan?” Lagi, aku tak membalasnya.
“Jadi, sampai kapanpun posisi Andre
nggak akan tergeser dari hatimu, begitu? Huh, Aku kira aku dapat mengisi
tempatnya setelah semua ini,” ia tersenyum sinis.
Kala ia mulai membawa Andre dalam
percakapan ini, emosiku meninggi dengan sendirinya.
“Mas, cukup, memasukan Andre dalam
obrolan, kalau ingin bahas tentang aku, ya bahas ini, Mas.”
“Tapi perasaanmu terikat dengan
Andre, jadi namanya tak luput ku sebut,” ia membalas dengan cepat. “Lagian,
kenapa sosoknya begitu kokoh tertanam di hatimu, La? Kamu punya aku di sini
yang juga telah jatuh hati padamu, dan siap menafkahimu lahir batin.”
“Jadi, maksud Mas, Andre nggak siap
untuk menafkahi aku?” Nada suaraku sedikit meninggi.
“Aku melihatnya demikian. Aku juga
beberapa kali menengok isi feed instagramnya. Ia seakan belum punya konsep
hidup yang matang. Jiwa mudanya masih nampak terlalu dominan sehingga
menjadikan ia sedikit liar. Dia juga---“
“CUKUP!!!!” Seruku lantang. Aku
melihat sejenak ke arah bawah, ada seorang remaja yang menengadah ke arah kami.
Biarlah, aku hanya perlu menghentikan omongan Mas Fahri.
“Mas...kamu nggak tahu apa-apa
tentang Andre. Jangan mengatakan apa-apa yang tidak kamu ketahui betul, Mas,”
aku mencoba merendahkan suaraku kembali.
“Then tell me, La, what makes him so special in your eyes?” Balasnya.
Aku berpikir sesaat. Should i tell him now?
“Hati ini nggak bisa memilih kepada
siapa ia akan berlabuh. Saat bertemu dengannya, aku adalah sosok yang rapuh.
Bersamanya, aku merasa memiliki malaikat pelindung. Meninggalkannya, hatiku
serasa mati. Kamu bisa bilang ini semua hanya omong kosong, tapi kamu tahu apa,
Mas? Aku yang merasa, kamu tak berhak menilai,” jawabku dengan bibir gemetar.
“Kita sudahi saja pembicaraan ini.”
Aku melangkah meamsuki apartemen
meninggalkan sosoknya yang mematung. Aku tak ingin air mata ini sampai tumpah
di hadapannya, karena air mata ini siap keluar dari bendungannya.
“Lalu apa ada jaminan kalau dia
masih menerima kehadiranmu setelah kamu menghilang sekian lama dan
membohonginya sekian banyak?!” Ujarnya setengah berteriak.
Kakiku tertahan mendengarnya. Ia meneruskan
kalimatnya. “Belum pasti dia masih mencintaimu sama seperti terakhir kali kamu
meninggalkannya, terutama setelah ia mendengar apa yang telah terjadi, La.”
Aku berbalik arah menghadapnya.
“Satu hal yang pasti, Mas, hubungan ini akan segera berakhir dan aku nggak
perlu ragu lagi untuk mengucapkan ini. Sebaiknya kita segera pulang, kita urus
perceraian kita,” ujarku dengan suara parau.
Senja di Avignon perlahan dilahap
kelamnya langit malam. Petang itu, air mataku luruh bersama dengan hilangnya
Avignon dari hati.
to be continued