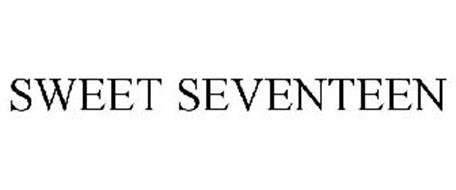Chapter I-V bisa di klik pada tags 'Series'.
---
Andre
Banyak peristiwa besar yang terjadi dalam semalam, kemudian merubah hidup mereka yang bersangkutan dengan peristiwa itu setelahnya. Seperti kisah para creator saat ciptaannya berbuah manis. Berawal dari puluhan, ratusan hingga ribuan kali percobaan dan pada akhirnya menghasilkan satu keberhasilan. Keberhasilan yang menutupi kisah perjuangan dibaliknya. Keberhasilan yang menasbihkan nama mereka ke dalam daftar manusia berhasil.
Cerita serupa juga terjadi pada gue, namun yang membedakan gue dengan creators itu ialah mereka mengawali kisah dengan kegagalan, lalu berakhir dengan luar biasa. Sedangkan kisah gue diawali dengan hal-hal indah dan hanya dalam semalam kisah tersebut berubah menjadi mimpi paling buruk selama hidup gue.
Dering ponsel menyadarkan gue dari lamunan terkait masa itu. Panggilan dari Ivan, adik gue.
“Halo,” gue membuka percakapan.
“Lagi dimana, Bang?” Tanyanya tanpa basa-basi.
“Di kafe, kenapa?”
“Lagi ada siapa?”
“Berdua sama Rama, kenapa?” Satu pertanyaan lagi keluar dari bibirnya, gue berniat mendaftarkan dia ke redaksi surat kabar lokal sebagai wartawan.
“Sip! Gue ke sana ya, Bang! Jangan pergi dulu!” Ujarnya penuh semangat. Niat mendaftarkannya sebagai wartawan pun gue urungkan.
Ivan mematikan sambungan telfon. Gue meletakkan ponsel pada tempat semula. Meraih gelas berisi kopi dan menyeruputnya perlahan.
“Ivan?” Tanya Rama disusul kepulan asap yang keluar dari rongga mulutnya. Gue jawab pertanyaan tadi dengan anggukan lemah.
“Ke sini?” Gue mengulangi hal yang sama.
“Mau ada yang diobrolin sama lo kayaknya. Semangat banget dia pas tau ada lo di sini,” ujar gue.
“Paling cewek lagi,” sahut Rama kembali menghisap vape dari genggamannya.
“Iya kali,” ucap gue singkat.
“Lemes amat lo.”
“Kapan lo liat gue semangat?”
“Pas di panggung,” Rama tersenyum tipis. “Meskipun gue tau itu bukan 100 persen semangat manggung, tapi cuma ajang buat lo numpahin emosi yang kerap lo tahan.”
Gue meresponnya dengan diam. Apa yang barusan ia katakan ada benarnya. Panggung adalah satu-satunya tempat bagi gue untuk melampiaskan penderitaan gue. Dan Rickenbacker kesayangan gue merupakan media yang tepat untuk menyalurkan penderitaan tersebut keluar lalu menguap bersama musik yang berdentam dari sound, serta riuh-remah penonton ketika ikut bersuara mengikuti vokal dari Rama.
“Bang Andre sama Bang Rama ada di tempat biasa,” terdengar sayup suara Ben, barista di sini, menyebut nama gue dan Rama, menandakan bahwa Ivan telah sampai.
Gue bisa melihat Ivan berjalan ke arah kami dari pintu kaca yang menghubungkan bagian luar--smoking area, dengan bagian dalam kafe. Raut wajahnya terlihat sumringah. Senyum yang tersungging dari bibirnya selama ia berjalan malah membuat dia terlihat seperti seseorang yang kehilangan akal. Timbul pikiran menghubungi Ibu lalu mengatakan untuk mencoret nama Ivan Rizki Dwiputra dari daftar nama kartu keluarga.
“ASSALAMUALAIKUM ABANG-ABANG SEMUA!” Ia membentangkan kedua tangannya tepat setelah membuka pintu kaca. Teriakannya sungguh memekikan telinga. Gue menjawab salamnya lirih.
“Berisik tai,” umpat Rama.
“Hehehehe, ya maaf, Bang. Lagi semangat nih.” Ivan menempati kursi kosong di sebelah gue.
“Gue tebak, pasti ada hubungannya sama cewek nih kalau semangat begini,” ujar Rama sembari menyesap kopinya yang mulai dingin.
“Hehehe, emang segitu keliatannya, ya?” Ivan nggak berhenti cengengesan. Kalau dia sudah seperti ini dan kita sedang berada di tempat ramai, gue kerap mencabut status dia sebagai adik kandung.
“Karena lo kayak orang bego, Dek, kalau udah berhubungan sama cewek,” sambung gue. Ivan tetap tertawa. Gue mau lempar tisu ke dalam mulutnya.
“Udah, gue tau tujuan lo ke sini. Mana coba fotonya, biar gue liat orangnya gimana,” sahut Rama sembari menjulurkan tangannya.
“Bentar, Bang,” Ivan mengeluarkan ponselnya dan ia mulai tenggelam dengan aktifitas mencari foto ‘gebetannya’ tersebut. “Nih.” Ia menyerahkan ponsel kepada Rama.
Rama menatap layar ponsel lekat. Matanya memicing memerhatikan foto yang diberikan Ivan. Ia berulang kali mengernyitkan dahi, juga jemarinya tak henti mengelus janggut lebatnya berulang-ulang. Seolah ia sedang berpikir keras.
“Si kampret, ini mah Nabela,” ujar Rama.
Ivan melotot. Gue spontan tertawa.
Gue hafal betul siapa Rama. Seorang womanizer merangkap playboy yang sudah terkenal sejak SMA. Gue rasa nggak ada cewek cantik yang nggak dikenal Rama. Dan bagi kami, personil Alchemy, serta beberapa orang yang kenal dekat dengannya, termasuk Ivan, bukan suatu hal yang asing apabila tahu bahwa ia kerap ‘tidur’ dengan beberapa dari mereka. Pesona serta auranya sebagai frontman dari Alchemy mampu membius gadis-gadis tersebut. Hal ini menjadikan Rama sebagai ‘guru’ oleh Ivan dalam hal wanita. Namun, apabila Ivan mengikuti jejak guru sablengnya tersebut, maka gue sungguh-sungguh untuk menurunkan kastanya sebagai seorang adik.
Butuh beberapa saat bagi Rama untuk menyadari alasan gue tertawa serta arti dari tatapan Ivan kepadanya. Lalu ia menepuk jidatnya dan mulai tertawa.
“Tenang, Van, gue cuma pernah liat foto dia di instagram UI cantik, kok. Kalem, kalem, hahaha,” tawanya mengeras. Perut gue bahkan mulai sakit karena terus-menerus tergelak. Ivan mengalihkan tatapan jengkelnya ke gue. Seakan menyuruh gue untuk diam dan tidak ikut-ikutan memojokkannya.
Ivan menatap tajam Rama dan masih tanpa suara. Ia masih belum sepenuhnya percaya pada kata-kata Rama. Ia nggak sepenuhnya salah kalau bersikap begitu, andai gue ada di posisi Ivan pun gue nggak akan gampang percaya dengan apa yang Rama katakan.
“Yeee si tai, beneran gue nggak kenal, cuma tau doang. Cantik emang anaknya, ya masih cocok lah kalau sama lo,” jelas Rama sambil menyeka air matanya yang keluar akibat tawa tadi.
“Mana coba, Dek, gue mau liat,” gue meraih ponsel yang diserahkan Ivan. Gue tatap foto itu sejenak. Cantik. Banget. Itu yang pertama terlintas dipikiran gue. Ivan melihat gue, menunggu tanggapan dari kakaknya. Tawa Rama mulai mereda.
“Ini bukannya yang waktu itu lo omongin, Ram? Pas abis manggung di Semarang itu loh.” Gue mengucapkannya dengan menahan tawa. Ivan terbelalak, sedangkan tawa Rama kembali pecah.
“Jahat bener lo sama adik sendiri,” Rama memegangi perutnya yang bergejolak. Ivan nampak mulai pasrah sebagai pihak yang tersudutkan. Dan memang sudah seharusnya seperti itu. Pasrah dalam menjadi target bulan-bulanan dari kakaknya beserta teman-temannya.
“Bercanda, Dek, cantik kok,” gue meletakkan ponsel itu di atas meja sambil tersenyum padanya. “Ini lo baru mau kenalan atau emang udah deket?” Tanya gue mencoba serius.
“Udah lumayan deket bang,” suaranya masih terdengar layu.
“Lemes amat woy! Becanda doang kampret. Gue beneran kagak kenal sama dia,” Rama melempar tisu yang tergumpal pada Ivan. Mendengar hal itu secara perlahan senyum di wajahnya timbul kembali dan ia mulai terkekeh.
“Kan, begonya kumat,” tambahku.
---
Setelah Ivan meninggalkan kami berdua kembali, aku terhanyut dalam kesunyian panjang. Kesunyian dalam hati yang lahir dua tahun lalu dan mendekam di dalamnya hingga kini.
“Perasaan baru kemarin dia curhat ke gue tentang hubungannya sama Laura, sekarang udah nunjukin foto yang baru aja,” dengan bersandar pada dinding, Rama mengulangi kegiatannya mengepulkan asap ke ruang kosong di langit-langit. Matanya menatap kumpulan asap itu.
“3 bulan lalu kalau nggak salah. Gue inget karena dia terus-terusan nanyain lo. Bawelnya minta ampun itu anak,” gue terseyum getir.
“Dia aja udah nemuin destinasi selanjutnya. Lo sendiri gimana?” Rama mengubah pandangannya ke gue.
Telak.
Gue tatap Rama tanpa mampu mengeluarkan kata-kata. Pertanyaan tadi cukup menohok hati gue.
“Udah 2 tahun, bukan? Mau sampai kapan?” Terusnya.
Gue membuang muka. Memerhatikan customer yang datang dan sibuk dengan aktifitas masing-masing di mejanya. Sudah dua tahun. Gue bahkan nggak menyadari kalau waktu berjalan sedemikian cepatnya. Namun, rasa sakit itu masih terasa seperti kemarin.
“Entahlah, Ram. Baru juga dua tahun. Sejauh ini masih nggak ada yang berubah,” gue berbicara tanpa memandangnya.
“Asal lo tau, Ndre, tiap kali Ivan curhat masalah kehidupan cintanya sama gue, sebenarnya gue pun nggak bisa ngasih banyak saran. Dia mungkin cuma ngeliat dari gue sebagai orang yang tau banyak karakteristik perempuan, tapi level percintaan gue masih jauh di bawah lo. Maksud gue, kalau mau ngomongin hubungan yang serius sama satu wanita, lo orang yang tepat, bukan gue,” jelas Rama. Bibir gue masih terkatup.
Lagi. Kata-kata yang meluncur dari mulutnya sebagian besar adalah kenyataan. Walaupun ia tahu mengenai seluk beluk wanita, tapi ia tak pernah menjalani hubungan yang serius. Rekor terlama ia berpacaran yaitu saat SMA dengan manajer kami, Dian. Setelahnya ia hanya berapacaran tidak pernah lebih dari satu semester, atau bahkan hanya sekedar one night stand.
Sudah dua tahun sejak hari itu. Hari dimana ia mulai menghilang. Hari saat Laila Indrayanti, seseorang yang sangat gue sayangi pergi tanpa meninggalkan kabar satupun. Pada awalnya gue mengira ia hanya sedang pergi ke suatu tempat dan ponselnya tertinggal, hingga lupa menghubungi gue. Namun, kabar darinya tak kunjung datang sampai beberapa hari ke depan. Sampai akhirnya gue tersadar bahwa dia telah berada di luar lingkaran hidup gue.
Panik? Jelas.
Gue terus mencari keberadaannya, hingga detik ini. Meskipun intensitasnya kini berkurang. Tapi hasilnya tetap nihil. Ia seperti hilang ditelan bumi. Dia tidak memperbaharui isi dari tiap sosial media yang dia punya selama dua tahun terakhir. Termasuk saat instagram memperkenalkan fitur stories mereka, ia tidak pernah menggunakannya.
Padahal gue selalu menunggu untuk itu.
Setidaknya untuk sekedar tahu bahwa ia dalam keadaan baik-baik saja.
Gue pun sempat punya pikiran bahwa ia menjadi korban penculikan dan pembunuhan. Bukannya gue berharap kalau hal itu benar terjadi, tapi saat seseorang menghilang secara tiba-tiba dan tidak ada kabar lagi setelahnya, apakah mempunyai pikiran demikian termasuk naif? Gue beropini itu masih masuk diakal. Atau jika tidak, mungkin gue yang perlahan menjadi gila karenanya.
Saban hari gue menghabiskan waktu dengan browsing dan menonton berita. Mata gue terfokus tiap berita kriminal ditayangkan. Membaca tiap headline dan running text. Berjaga-jaga andai ada berita mengenai seorang wanita berumur dua puluh lima tahun tewas dibunuh setelah sebelumnya diperkosa dan jasadnya dibuang di pinggir jalan tol, di sana. Kabar tersebut tak urung tersiar. Setelah gue menampar diri sendiri, gue mencoba membuang pikiran busuk ini dan berdoa untuk keselamatan Laila dimanapun ia berada.
Saat gue bertanya kepada kawan dekatnya, Nadine, ia menampik kalau tahu keberadaan Laila, sahabatnya dan, ugh, mantan? Atau masih pacar gue? Entah bagaimana gue menyebutnya. Kami tidak berpisah selayaknya sepasang kekasih memutuskan hubungan. Tapi dengan kepergiannya yang tiba-tiba tanpa meninggalkan sepatah kata, gue pun nggak yakin kalau ini bisa disebut ‘putus’.
Dan sebagian dari hati gue yang masih bertahan dengan kondisi ini mengatakan bahwa Laila masihlah milik gue. Mesikpun sisi lainnya sedikit demi sedikit kehilangan kesabaran akan penantian yang tak berujung ini.
Gue sadar kalau gue nggak segitu bego dalam urusan cewek. Gue tahu Nadine selalu menghindar acap kali gue bertanya mengenai Laila. Gue cuma bego dalam usaha menyampaikan apa yang ada dipikiran gue kepada seseorang. Dan saat orang tersebut nggak mau memberitahu apa yang terjadi, gue berhenti bertanya kepadanya karena kerap timbul perasaan nggak enak. Ini menjadi ketololan gue yang lain.
Hal tersebut sering terjadi saat dulu gue dan Laila masih bersama.
Huh, masih bersama... Kata itu terdengar aneh bagi gue.
Dulu, Laila selalu menghindar apabila gue bertanya mengenai hal yang sedang tidak mau dia bahas dan gue selalu menerima itu. Termasuk dengan yang dilakukan Nadine kepada gue, sampai gue memutuskan untuk nggak lagi bertanya padanya.
Setelahnya, ia terlihat mencoba membantu gue dalam berbagai hal—mungkin untuk menambal perasaan nggak enak ke gue, juga termasuk saat gue memutuskan untuk membangun kafe yang gue idamkan. Nadine turut serta dalam proses pembangunannya. Ia banyak memberi masukan dari segi manajemen serta pelayanan, karena ia punya pengalaman lebih dulu di bidang yang sama. Juga kebetulan terdapat kesamaan dari konsep kafe kami, yaitu terdapat live music di dalamnya.
Kafe yang gue bangun ini dulu sering gue diskusikan dengan Laila. Gue mengatakan bahwa suatu saat nanti gue akan membangun sebuah kafe yang merepresentasikan pertemuan kami pertama kali.
“La, setelah lulus nanti, aku rencananya mau bikin kafe sendiri deh di Serang,” ucap gue saat gue dan Laila duduk berhadapan di sebuah kedai kopi asal Amerika yang terletak di pelataran gedung bioskop tepi jalan Urip Sumoharjo pada penghujung tahun 2014 lalu.
“Sejak kapan kamu punya pikiran itu?” Ujarnya sambil meminum caramel macchiato miliknya.
“Sejak pertemuan kita pertama kali. Entah kenapa aku merasa punya utang budi ke semua kafe-kafe yang ada. Karena adanya mereka, kita bisa bertemu di salah satu diantaranya,” gue menatap tepat pada titik bola mata indahnya. Mata teduh yang selalu membuat jiwa gue merasa tenang.
“Kamu bisa nggak lebay gak, Ndre?” Ia terkekeh.
“Ini serius, La. Lagi pula di kotaku masih jarang kafe yang benar-benar kafe. Maksudku yang menyediakan kopi signature-nya sendiri. Yang benar-benar enak buat catching up sama teman lama, pacar, gebetan ataupun selingkuhan.”
“Jadi kamu mau bikin kafe buat ketemu sama selingkuhan kamu?” Entah kenapa dari omongan gue yang panjang tadi, ia hanya menangkap bagian akhirnya saja.
“Eng...”
“Hayo ngaku!”
“Buk...”
“Ngaku gak?”
“La...”
“Apa?!”
“Denger-denger diskon akhir tahun di Amplaz udah mulai, ya? Mau belanja?”
Hening.
Selang beberapa lama, Laila ketawa dengan kerasnya. Membuat beberapa pengunjung lain menoleh ke meja kami.
“Kamu tuh, ada aja pikirannya. Niat aku cuma mau bercandain kamu. Aku seneng aja ngeliat muka kamu yang kalau nggak salah tapi aku salahin tuh lucu jadinya,” ucapnya masih dengan tertawa, namun kali ini satu tangannya menutupi mulutnya. Ketawa cantik kalau kata orang-orang. Padahal, sesaat lalu caranya tertawa udah mirip nenek lampir. Tapi ia cepat sadar kalau sedang berada di tempat umum. Jaga image, katanya. Tawa nenek lampir tadi cuma terlihat saat kami sedang berduaan saja.
“Hahaha, iya tau kok kamu cuma bercanda. Udah hafal juga aku,” gue pun ikut tertawa. Menghargai candaannya demi keselamatan jiwa.
Laila yang masih tertawa dengan tangan memegang cup caramel macchiato-nya tiba-tiba menghentakkan cup tersebut ke meja dengan cukup keras. Tawanya terhenti. Mata indahnya berubah menjadi mata nenek lampir sungguhan dan menatap tajam menghunus bola mata gue. Auranya berubah hanya dalam hitungan detik. Ia membuka mulutnya, “Tapi ajakan belanja kamu tadi bukan bercandaan, kan?” Gue nelen ludah.
---
“WOY!”
“Wah, gila ini orang.”
“Bang, gimana nih? Panggil ustadz aja? Kayaknya kesurupan deh.”
Gue terperangah mendapati Rama, Ben, Fajar, Alika, Richard bahkan Ivan yang tadi sempat pergi, sekarang tengah berada di hadapan gue dengan masing-masing melayangkan tatapan heran.
“Ada apa nih rame-rame?” Tanya gue.
“Wah, sadar juga nih orang, kirain udah gila,” sahut Richard.
“Kenapa sih?” Jawab gue polos.
“Oy kampret, gue udah panik tadi. Lo bengong lama banget, gue kasih cipratan air lo nggak sadar. Gue goyang-goyangin juga nggak sadar. Terus gue panggil Ben, Fajar sama Alika buat bantu, masih nggak sadar juga. Gue minta bantuan di grup Alchemy yang bisa dateng si tai Richard doang. Akhirnya gue nyuruh Ivan buat balik lagi biar jadi saksi kalau kakaknya udah gila,” jelas Rama panjang lebar.
“Kampret, gue udah dateng masih aja dikatain,” timpal Richard.
“Eh? Serius? Duh, maaf-maaf jadi ngerepotin kalian gini,” gue menggaruk bagian belakang kepala sambil memasang muka nggak enak kepada mereka. Apa selama itu gue melamun? Apakah hanya gegara seorang perempuan bisa menghancurkan mental gue?
Rama mengambil tempat di sebelah gue, lalu melingkarkan lengannya melewati leher. “Take it easy, bro. Jangan lo jadiin beban. Percaya aja kalau ini memang udah bagian dari rencana Tuhan. Dan percaya bahwa suatu saat nanti datang seseorang yang bisa menggantikan posisi Laila di hati lo. Lo punya kita, Ndre,” ia berhenti sejenak, matanya menyapu mereka yang berdiri di hadapan kami. “Kalau gue atau anak-anak Alchemy nggak bisa bantu, masih ada Ben, Fajar sama Alika yang stand by di kafe. Gue tau si Ivan nggak bisa diandelin buat masalah kayak gini, tapi setidaknya sosok dia nyata, Ndre. Dan yang pasti lo nggak sendirian.”
“Nyesel gue dateng, Bang,” sesal Ivan mendengar perkataan Rama.
Gue tersenyum. Kembali ia berkata benar. Gue rasa Rama lah yang seharusnya dikira kesurupan, karena hari ini apa yang ia katakan banyak benarnya.
Gue nggak sendirian. Meskipun gue ragu akan perkataan Rama tadi yang membawa nama Tuhan padahal ia sendiri termasuk orang yang tidak taat beragama. Namun ketika gue menatap mereka yang kini berdiri di sekeliling gue dengan raut wajah khawatir, gue sadar mungkin sudah seharusnya gue berdamai dengan masa lalu dan mulai menyusun rencana ke depan serta menapakinya dengan perlahan.
“Mau dilepasin di panggung aja? Biar lo nggak gila beneran,” ajak rama yang segera gue iyakan.
---
Berbeda dengan kafe milik Nadine yang memilih menampilkan live music berupa penampilan akustik, gue lebih kepada penampilan band bagi siapa saja yang mau mengisi. Termasuk Alchemy yang kerap tampil di kafe ini yang ternyata mampu menarik minat pengunjung lebih banyak.
“Mau main apa?” Ujar gue sambil mempersiakan amplifier. Richard bersiap pada posisinya dibalik drum. Begitu pula dengan Rama bersama gitarnya.
“Yellow Ledbetter-nya Pearl Jam, gimana?”
“Mainkan!” Sahut Richard dari belakang.
---
Mungkin gue harus merelakan Laila.
Mungkin.
Tapi, apakah gue sanggup?
to be continued