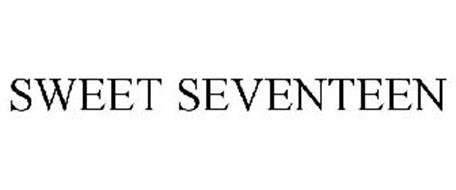Kebahagiaan bagiku adalah suatu hal yang sifatnya abstrak. Parameter kebahagiaan tiap individu pun berbeda. Ada yang bahagia hidup dengan materi berlimpah. Atau yang bahagia hanya dengan bersama orang yang dicintainya, bagaimanapun kondisi materi yang ia miliki. Juga ada yang rela meninggalkan kehidupan yang mungkin menurut orang lain merupakan kehidupan yang ideal, namun tidak baginya, sehingga ia memutuskan mencari kebahagiaannya kembali, kebahagiaan lamanya.
Dan akulah orang itu.
Aku menemukannya, kebahagiaan lamaku. Melihatnya sejelas janji yang dulu pernah terucap dari bibir kami. Aku menemukannya, namun tak memilikinya.
Dia keluar begitu jarum panjang dan pendek pada jam menyatu di angka 12. Menyapa dua orang yang tak ku kenal, kemudian pergi dengan menaiki skuter matik hitam yang tak asing bagiku. Sosoknya segera lenyap dari pandanganku seiring menjauhnya pantulan cahaya dari back lamp skuter miliknya.
Aku masih terpaku di belakang kemudi mobil. Membayangkan sosoknya yang pergi tanpa pernah sempat melirik ke arahku. Bodoh, tentu dia tak mengenali mobil ini. Mobil yang aku kendarai kini bukanlah mobil yang sama seperti yang diketahuinya dulu. Bukan mobil yang sempat membuatnya kesal karena pernah kutinggalkan dengan bensin yang sudah hampir habis. Dan tentu, siapalah aku sekarang berharap ia melirik ke arahku?
Lima belas menit kuhabiskan dengan termenung. Setelah menarik nafas dalam, aku melajukan mobil menyusuri jalanan kota kecil ini, kembali menuju tempatku menginap selama 4 hari terakhir. Aku tahu, ini sungguh membuang-buang uang. Tapi aku tak sanggup meninggalkan kota ini tanpa bertemu dengannya. Namun, aku tak punya cukup keberanian untuk menegurnya kembali.
Sesampainya di kamar, aku merebahkan diri di atas kasur sembari membuka ponsel yang sedari tadi tak kusentuh. Aku mendapati 38 chat Line serta 14 misscalls dari kontak yang sama, satu-satunya orang yang tahu akan keberadaanku selama ini serta menepati janjinya untuk tidak membocorkan hal itu kepada siapapun, termasuk Andre.
Misscall terakhir tercatat 7 menit lalu. Aku memutuskan menghubunginya kembali.
“Halo,” sapaku.
“Babe, kok baru respon sih? Gue coba hubungin lo dari tadi juga,” sahut suara di ujung telefon hampir bersamaan dengan sapaanku.
“Sorry, Nad, gue baru megang hp lagi. Tadi lagi pengin sendiri aja, jadi hp gue silent, maaf ya.”
“I’m worried about you, La. Gue takut lo kenapa-napa, apalagi lagi di kota orang kan,” senyumku tersungging mendengarnya.
“Iya, gue minta maaf sekali lagi. Thanks for caring me, Nad.” Kadang, aku sempat berpikir bagaimana jika Nadine tidak ada di hidupku? Sosoknya sangat sentral terutama dalam 2 tahun terakhir. She’s always got my back. Dia bahkan tetap memberi saran terbaiknya kala aku membuat keputusan yang seharusnya tidak dapat dimaafkan orang lain. Dia selalu siap menampung cerita dan tangisku. Tak ada tawa yang aku bagi dengannya. Bukan, bukan berarti aku hanya datang padanya when i’m feeling blue, melainkan aku merasa bahwa aku dan bahagia sudah berpisah sejak aku meninggalkannya. Meninggalkan Andre.
“Okay, tapi lain kali jangan gitu lagi ya, La?” Ujarnya kembali.
“Iya, Bu,” balasku singkat.
“Nanti tiap satu misscall dari gue, itu berarti lo hutang satu ice cream sama gue,” sambungnya yang membuatku spontan tertawa.
“Heh! Ngide banget ya ini orang. Main sembarangan nentuin rules. Enggak... Enggak, nanti lo sengaja lagi nelefon gue terus dimatiin biar jadi misscall dan lo akhirnya dapet ice cream gratis,” jawabku menahan tawa.
“AAAH LAILAA! Lo kenapa bisa baca pikiran gue sih? Ah, nggak asih niiih,” ia histeris sendiri. Nadine tahu bagaimana membuatku tertawa ditengah himpitan kesedihan ini.
“Gue kenal lo bukan sehari-dua hari sayaaang. Gue khatam gimana liciknya lo, hahaha,” ucapku.
“Gue licik juga karena bergaul sama lo, ya, La!!” Jawabnya ngotot.
“Gue? Licik? Jangan sembarangan yaa!” Sergahku masih dengan tawa terselip di antara pembicaraan kami.
“Udah, ah, udah. Jadi lupa, kan, gue mau nanya apa tadi.”
“Makanya seimbangin kerja sama refreshing-nya, bu. Kasihan otak lo, kinerjanya jadi nurun gitu. Alhasil lo jadi gampang lupa deh,” aku mendengar ia terkekeh. “Gue ingetin deh, lo mau nanya tadi gimana, kan? Gue berhasil ketemu Andre atau engga, kan?”
“Tapi seinget gue, gue belum bilang apa-apa deh tadi. Kok lo bisa tahu?” Tanyanya heran.
“Karena lo selalu menanyakan pertanyaan yang sama selama 4 hari terakhir ini,” jelasku.
“Eh? Iya, ya? Gue lupa, hahahahahaha,” kembali aku tersenyum mendengarnya.
“Gue jawab, ya? Jawaban yang sama dengan kemarin kok,” aku tersenyum getir.
“Kenapa, La? Kenapa nggak dicoba dulu?”
Kenapa? Katanya. Aku sendiri tak tahu. Seperti ada gaya gravitasi yang begitu besar yang menahanku agar tak beranjak dari balik kemudi mobil. Atau memang aku yang terlalu malu untuk menampakkan batang hidungku di hadapannya.
2 tahun lalu, aku pergi tanpa bertatap muka dengannya. Bahkan, tanpa ucapan selamat tinggal. Sebenarnya aku ingin, tapi aku tak mampu. Aku tak tahu bagaimana cara mengucapkannya. Dan tentu, aku tak ingin menangis dan melihatnya menangis andai waktu itu ia melihat kepergianku.
“La, gimana kalau lo coba ngasih kabar ke salah satu temannya? Setidaknya nggak semua dari mereka kaget dengan kehadiran lo yang tiba-tiba, kemudian men-judge lo sebagai perempuan nggak tahu diri yang udah bikin sahabat mereka hancur hatinya. Biarin salah satu dari mereka tahu alasan kenapa lo sempat pergi dan kini kembali,” hmm, masuk akal. Tapi kepada siapa aku harus bicara? Dian? Mungkin ia akan mengerti karena perasaan sesama wanita, namun ada keraguan yang menahan keyakinanku jika harus menyampaikan hal ini kepadanya. Atau Rama? Dari semua personil Alchemy, dialah yang terdekat dengan Andre. Mungkin dengannya aku harus berbicara. Ah, biarah kupikirkan lagi nanti.
“Hmm, gue pertimbangin deh, Nad. But, thanks for the advice.”
“Lebay ih pakai makasih segala. By the way, nggak kerasa udah jam setengah dua aja. Ngobrol sama lo selalu kayak masuk mesin waktu, La,” ucapnya diiringi tawa kecil.
“Hahaha, yaudah lo istirahat gih. Kasian juga gue, lo capek seharian ngurusin kafe, setelahnya juga ngurusin gue. Makasih lagi, ya, Nad. Gue sering banget ngerepotin lo,” ujarku tak enak.
“Duh, La, beneran deh.. Sekali lagi lo bilang makasih, lo harus traktir gue ice cream kalau ketemu nanti.”
“Makasih ya, Nad,” balasku.
“Buat ini gue yang bilang makasih, La, karena udah ditraktir ice cream sama lo,” aku yakin kami berdua tersenyum pada saat bersamaan.
---
Aku berada di satu-satunya McDonald’s di kota ini, duduk di bagian luar karena orang yang kutunggu merupakan seorang perokok berat. Sembari menunggunya datang, aku ditemani oleh satu cup McFlurry Oreo kesukaanku. Sebenarnya aku sedikit ragu untuk bertemu dengannya, terlebih setelah semua yang terjadi terhadap kawan baiknya. Namun, pasca mengumpulkan keyakinan lebih serta mendapat dukungan dari Nadine, maka aku putuskan untuk menghubunginya dan di sinilah aku sekarang.
Tak lama kemudian sosok yang kutunggu tiba. Seorang pria dengan rambut gondrong yang diikat serta brewok lebat yang menghiasi wajahnya, seakan mempertegas penampilannya sebagai seorang rockstar. Tak ketinggalan, sebatang rokok terselip pada mulutnya. Segera aku melambaikan tangan ke arahnya.
“Laila?” Ujarnya saat ia berdiri di hadapanku. Kehadirannya sungguh menarik perhatian orang-orang yang sedang sibuk melahap makanannya. Aku merasakan bagaimana banyak mata terpaku pada sosoknya semenjak ia turun dari mobil, maklum vokalis band ternama. Dan kini sorotan-sorotan itu beralih padaku, mereka seakan bertanya siapa gerangan perempuan yang dihampirinya.
Ia mengambil tempat di depanku, “Sorry, gue agak pangling ngeliat lo. Kelihatan beda sama terakhir gue liat atau gue aja kali yang lupa, ya? Maklum udah lama juga,” ujarnya.
“Iya, gue manjangin rambut gue, jadi wajar kalau lo pangling gitu,” jawabku dengan senyum canggung. “Mau order dulu?” Tanyaku mencoba menghilangkan perasaan tak enak ini.
Ia menghisap rokoknya kuat, kemudian menghembuskan asap tebal ke udara. “Nanti aja,” sahutnya singkat. “So?” Ia melanjutkan perkataannya, membaca alasanku mengajaknya bertemu.
“Ehm, okay. Sebelumnnya gue mau minta maaf atas apa yang gue lakukan ke Andre. Gue tahu, nggak seharusnya gue ngilang gitu aja dari kehidupan dia. Dan mungkin lo udah bisa nebak apa alasan gue sekarang ada di sini. Dan mungkin juga lo berpikiran bahwa gue cewek nggak tahu diri yang bisa pergi lalu kembali seenaknya gitu aja. Tapi, Ram, gue punya alasan dibalik itu semua,” aku terdiam sejenak setelah kurasakan emosiku kembali naik mengingat sebenarnya aku tidak sanggup untuk menceritakan ulang semua kisahku. Mengingat betapa bersalahnya aku atas apa yang terjadi pada Andre selama dua tahun kepergianku.
Rama menatapku tajam, kembali ia membua kumpulan asap di udara sebelum berbicara, “Go on.”
Aku menghela nafas. “Gue akan ceritain semuanya dari awal, Ram. Mulai dari gue dan Andre belum bertemu. Harapan gue setelah menceritakan semua ini adalah kalau gue nggak berhasil ketemu Andre atau Andre nggak mau ketemu gue lagi, lo, sebagai sahabat terdekatnya bisa meyakinkan ia mengenai apa yang sebenarnya terjadi sama gue. Gue tahu, ini egois, banget. Tapi gue percaya sama lo, Ram. Lo satu-satunya harapan gue.” Rama tak bergeming. Keraguanku untuk menceritakan hal ini kembali menyeruak ke permukaan. Namun, aku rasa sudah terlambat untuk membatalkan semuanya.
Lantas aku bercerita mulai dari kehidupanku sebelum bertemu Andre, kemudian saat aku dan Andre berpacaran hingga aku pergi dari hidupnya, kehidupanku selama menghilang dua tahun ini, lalu mengapa kini aku datang kembali. Rama seorang pendengar yang baik. Ia memang cowok yang gemar bercanda, tapi Andre pernah bilang bahwa Rama dapat menjadi seorang yang serius ketika ada teman yang membutuhkan bantuannya dan saat ini ialah pembuktian atas apa yang pernah Andre katakan.
“Aaaargh, ribet bener,” ujarnya sambil mengacak-ngacak rambut sendiri. “Gue mau beli minum dulu deh. Lo yang cerita tapi gue yang pusing.” Ia berlalu ke dalam, meninggalkanku yang larut dalam emosi sehabis bercerita tadi.
“Nih, buat lo,” Rama menyodorkan satu cup McFloat padaku. Aku balas pemberiannya dengan ucapan terima kasih lirih.
“Cerita lo tadi bikin gue makin males ngejalanin hubungan yang serius. Terlalu ribet,” Rama berujar sembari menatap kosong ke arah dalam.
“Yah, jangan gitu dong. Ini hidup gue doang kok yang ribet, Ram, nggak semua cewek punya kehidupan seribet gue,” jawabku.
“Ribet. Males gue. Santai lah gue mah. Lo duluan aja sama Andre.”
“Gue? Andre? Gue aja belum berani buat ketemu dia, Ram. Dan nggak tahu juga gimana responnya nanti,” ucapku sambil mendengus pelan.
“He still loves you, La,” ia mengalihkan pandangan ke arahku. Aku tersentak mendengarnya.
“Sejak awal, gue udah punya jawaban dari semua pertanyaan dan penjelasan lo, La. Tapi sebelum gue bilang itu, gue mau tahu alasan dibalik lo pergi dan menghilang gitu aja hingga ngebuat hidup teman gue kacau,” Rama membuka segel bungkus rokok baru. Entah sudah berapa nikotin hari ini yang ia hisap.
“Dia pernah bilang gitu, Ram? If he still loves me?” Tanya gue memastikan.
“Enggak, tapi dia gue anggap gila karena udah nolak gue comblangin sama Arestika vokalisnya Barasuara. No offense, La, gue juga nggak bisa diam aja ngeliat sahabat gue galau terus-terusan, so, gue coba kenalin dia sama beberapa kenalan gue dan dia kayak, ‘sorry, Ram, gue nggak bisa,’ gue cuma bisa bilang, udah sinting nih orang nolak Arestika. Tapi dari cara ngomongya, gue tahu dia masih sayang sama lo,” mendengar Rama membuatku tanpa sadar tersenyum. Dan pada detik itu pula hatiku berujar, i’ll never go away from your life again, Ndre.
---
Akhirnya ku putuskan membawa langkahku menuju pintu itu.
Kronology Cafe. Nama yang tidak asing bagiku. Karena dulu, ia kerap mengutarakan keinginannya membuat kafe dengan nama demikian.
“Kronologi bagus nggak, La? Itu ngegambarin kita banget nggak, sih? Urutan kejadian pertemuan kita di awali dari kafe, kayak tiba-tiba aja gitu. Sebuah kronologi yang tercipta di dalam kafe, kayak magic-nya kafe gitu, La, when strangers become lover,” ujarmu kala itu disertakan dengan gerakan ‘imajinasi’ ala Spongebob yang membuatmu tampak lucu.
“Sounds great, Ndre,” ujarku sambil mengusap rambutmu. Aku selalu suka semangatmu. Karena aku tahu, kamu bukan tipe orang yang membiarkan mimpinya terhenti terkurung dalam batasan imaji. Saat sekarang aku berada di depan pintu masuk kafe yang dulu kamu gebu-gebukan, aku sudah tahu dari dulu bahwa kafe ini akan ada dan memang ada.
Jam di arlojiku menuju pukul 11. Kafe ini tutup kurang lebih satu jam dari sekarang. Kemungkinan sudah masuk waktu last order. Sengaja aku memilih selarut ini. Juga karena aku terlalu lama mengumpulkan keberanian untuk bisa sampai di sini, di depan pintu ini.
“Go for him. But promise me, you’ll never leave him again,” kata-kata Rama tadi siang terdengar kembali di dalam kepalaku. Aku menghela nafas. Ku dorong pintu dan melangkahkan kaki perlahan memasuki kafe.
“Selamat datang, Kak, silahkan mau order apa? Kebetulan kita sudah last order ya, Kak,” Sambut seorang wanita dari balik mesin kasir. Juga terdapat seorang barista sedang membersihkan mesin espresso dan seorang lagi sedang membereskan counter di belakang bar.
Dan aku melihatnya. Lagi. Dari jarak cukup dekat. Ia berada di ruangan khusus staff yang berada di bagian belakang bar. Ruangan itu terdapat kaca kecil pada dindingnya sehingga aku dapat melihat ia sedang membereskan beberapa barang.
“Aku order Laila Speciality,” ucapku dengan suara sedikit keras. Waiters itu tampak kebingungan mendengar pesananku, begitu pula dengan dua cowok di dekatnya. Mereka tampak saling bertukar tatap. Aku mengerti kebingungan mereka, tapi mataku terfokus pada gerakan satu orang lagi di ruang staff yang juga ikut terhenti.
“Eng... Maaf, Kak, kita nggak ada menu itu,” jawabnya terbata-bata. Aku masih mematung di depan bar dan tak melepas tatapanku dari sosoknya. Aku yakin menu itu ada. Dulu, Andre pernah mengatakan kalau ia akan menyiapkan satu signature drink khusus untukku dengan menggunakan namaku.
“Ada, Ka,” itu dia. Ia membuka suara.
“Eh? Serius ada, Bang?” Sahut waiters itu bingung.
“Iya, biar gue yang bikin. Disuruh duduk aja,” balasnya.
“Harganya, Bang?”
“Free,” sungguh, aku rindu mendengar suara itu. Namun tubuhnya masih belum beranjak dari dalam ruangan tersebut. Sementara dua orang lainnya masih terheran, lalu mereka menatapku yang kubalas dengan senyuman.
“Kak, silahkan duduk dulu, nanti pesannya diantarkan,” katanya disertai senyum canggung. Aku mengucapkan terima kasih dan mengambil tempat di bagian luar kafe.
Ini pertama kalinya aku berada di sini, tapi aku merasa tempat ini sangat tidak asing bagiku. Sebuah kafe dengan bentuk letter L ditambah mini stage di sebelah barat pintu masuk dan mengusung konsep low light seperti milik Nadine.
Aku tahu kalau panggung itu multi fungsi. Aku tahu bahwa bukan hanya penampilan band yang disajikan di sana. Aku tahu kalau band hanya ditampilkan tiap jum’at malam. Sedangkan di rabu malam akan ada sesi pembacaan puisi. “Ini kan kafe yang merepresentasikan kita, La, jadi aku mau ada part of you yang berhubungan dengan askara juga di sini,” begitu katamu dulu. Serta kamu memberikan tempat bagi komunitas stand-up comedy lokal untuk melakukan open mic setiap minggu sore. Aku memang baru pertama kali datang ke sini, like for real. But i feel like i’ve been here for whole time.
“Here's your coffee,” suara itu memecah lamunanku. Suara yang sangat ku rindukan kini terdengar sangat sangat dekat. Aku mendongkakkan wajah dan akhirnya aku melihatnya. Lagi. Ini merupakan jarak terdekat kami dalam dua tahun terakhir. Namun ia tidak memandangku. Ia menatap lekat cangkir kopi yang dipegangnya.
Lama kami terdiam, sampai aku putuskan untuk membuka perkataan, “Ndre..-“
“Kenapa?” Ucapanku langsung dipotongnya. Suaranya bergetar, begitu juga dengan cangkir dalam genggamannya.
“Kenapa baru sekarang?” Kini aku merasakannya. Luka karena kehilangan itu kini sangat terasa. Perasaan itu seketika menghujam relung hatiku dan mengingatkanku kembali terhadap dosa yang telah kulakukan padanya.
Aku berdiri dan memegang satu lengannya. “Can you take a seat? I want to talk, Ndre,” ia tidak menjawab, namun ia menuruti perkataanku. Sekarang, kita berada pada satu meja yang sama. Duduk berhadapan. Tanpa kata. Tanpa suara.
Andre masih belum menatapku. Matanya terpaku pada cangkir kopi yang terletak di antara kami. Tangannya mengepal erat menggambarkan bagaimana perasaannya. Aku tahu ia ingin bicara banyak hal dan aku pun tahu ia tak bisa melakukannya. Itu memang termasuk kelemahannya yang dengan kejam pernah ku manfaatkan.
Kini, aku rasa saat ini adalah waktunya. Waktu untuk menjelaskan segala yang terjadi. Waktu untuk membawa pulang perasaan yang pernah pergi. Meskipun dibutuhkan keteguhan dalam mendengar kenyataan yang akan ku utarakan sekarang, tapi aku rasa tak ada pilihan untuk menundanya lagi.
Aku menarik nafas panjang, lalu menghembuskannya perlahan.
“Ndre, i was married...”
to be continued