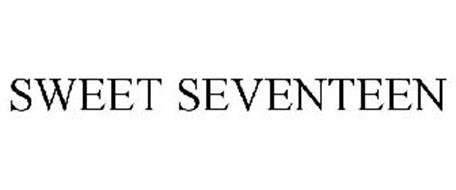Chapter I-IX bisa dibaca di sini
---
Laila
Prancis, 2015
Aku terbangun di sofa ruang tengah dengan kepala sedikit pening. Aku rasa, aku masih terkena jetlag meski sudah berada di sini selama dua hari. Ditambah, kondisi apartemen ini lebih layak dijadikan tempat syuting film hantu dibanding tempat singgah ketika pertama aku tiba, dan baru selesai kubersihkan siang hari tadi sehingga membuat energiku terkuras habis yang membuat aku tertidur di sofa sejak siang sampai menjelang malam hari.
Di perjalanan, Mas Fahri sudah mewanti kepadaku perihal kondisi apartemennya yang mengkhawatirkan. Aku menanggapinya dengan santai, ku pikir seorang berpenampilan necis sepertinya tak mungkin seburuk itu dalam mengurus tempat tinggalnya.
Hingga kami sampai di depan pintu, Mas Fahri kembali meyakinkan agar aku tidak sampai shock melihat berbagai barang berserakan dimana-mana.
“Ini orang lebay banget sih,” batinku waktu itu. Aku mengangguk yakin. Mas Fahri memasukan kunci ke lubang pintu, memutarnya perlahan hingga bunyi ‘krek’ terdengar menegangkan. Ia mendorong pintunya dengan pelan, leherku mendongak tak sabar memastikan perkataannya.
“ASTAGFIRULLAH!”
Aku tercengang. Mataku terbuka selebar-lebarnya, mulutku pun tanpa sadar sedikit menganga. Aku menatap Mas Fahri dengan mata memicing. Ia tertawa kecil dengan tatapan kan-udah-aku-bilang miliknya.
Aku tak menyangka hari pertamaku di negeri yang menjadi salah satu destinasi wajib di Eropa bisa seburuk ini. Pakaian kotor bertebaran disembarang tempat. Makanan yang belum dibuang sebelum Mas Fahri pulang ke Indonesia—yaitu dua minggu lalu, masih ada di posisi sama seperti sebelum ditinggalkan. Sampah makanan ringan serta kaleng minuman tergeletak begitu saja di meja depan televisi, bahkan hingga jatuh ke kolong meja.
Tak sampai di situ, kondisi serupa juga terpampang di dua kamar apartemen ini. Entah karena malas membersihkan salah satu kamar, sehingga Mas Fahri memilih tidur di kamar lain dan membuat kondisi sama buruknya di kamar itu atau memang sebelumnya tempat ini merupakan war zone bagi tentara Prancis. Aku tak habis pikir.
“Maaf ya, La, kemarin aku lagi ngerasa stres. Jadi nggak sempat membereskan ini semua.” Iya, Mas, aku juga stres karena harus berpisah dengan orang yang seharusnya mengenakan cincin yang sama denganku pada kondisi ini. Tapi seharusnya kamu juga mikir dong, Mas, kalau dalam waktu dekat akan ada perempuan yang menetap di sini untuk waktu yang tidak ditentukan.
Aku tak menyuarakan yang satu itu.
Setelah menempuh perjalanan selama hampir satu hari dari Jakarta menuju Marseille, kemudian ekstra enam puluh menit lagi perjalanan dengan TGV ke tempat tujuan akhir, Avignon, menjadikan tulang-tulang ditubuhku seakan terlepas semua. Hal ini membuat kekesalanku terhadap kondisi apartemen yang mengenaskan tersumbat sementara. Aku hanya menyingkap pakaian Mas Fahri yang berhamburan di atas kasur, lalu membanting tubuh ke kasur dan segera memejamkan mata.
Belum banyak aktiftas yang kulakukan selain membersihkan ruangan mengerikan ini. Namun tadi pagi tetangga sebelah barat apartemen kami, Leroy Devaux, datang dengan membawakan croissant terenak yang pernah aku makan. Ia tinggal bersama istrinya, Nathalie Devaux.
Melalui perbincangan singkat, aku mengetahui ternyata ia mempunyai boulangerie, atau toko kue, di Cannes, kota sebelah tenggara Avignon. Toko kue itu kini dikelola oleh putranya dan mereka tinggal di Avignon sejak 8 tahun lalu, membuka usaha home bakery lalu menjualnya dengan sistim door to door. Pelanggannya tak banyak, tapi mereka pelanggan yang setia karena rasa croissant atau baguette yang ditawarkan Leroy tak mungkin ditolak lidah mereka.
“Saya bisa sedikit bahasa Indonesia,” ujarnya dengan aksen khas bule yang mencoba pelafalan bahasa Indonesia. “Fakhri yang mengajarkan saya.” Aku tertawa pada caranya menyebut nama ‘Fahri’. Menurutku itu cukup lucu.
Leroy, pria 60 tahun yang kerap mengenakan flat cap tuk menutupi rambut putihnya, memiliki kontur wajah kotak dengan kumis putih yang menutupi setengah dari bibir atasnya. Tubuh tambunnya mungkin diakibatkan banyaknya alkohol yang ia konsumsi. Kepribadiannya hangat, sehingga saat berbincang dengannya aku merasa seperti seorang anak yang merindukan pembicaraan dengan ayahnya. Dan aku memang merindukan itu.
Leroy sadar aku belum menguasai bahasa Prancis sehingga dengan berbaik hati ia mengajakku bicara menggunakan bahasa Indonesia meskipun dengan cara bicaranya yang lucu dan terpatah-patah.
“Istri anak saya cantik seperti kamu,” ucapnya sambil tertawa renyah. Aku tersipu mendengarnya.
Obrolan terhenti mengingat masih banyak pekerjaan yang harus kulakukan. Leroy berjanji akan memberi kami kue buatannya selama seminggu ke depan, lalu minggu berikutnya kami harus membayar kue miliknya seharga dua minggu. Ia berlalu sambil tertawa meninggalkanku yang pula tergelak di ambang pintu.
Pasca seluruh pekerjaan rumah beres, aku beranjak ke dapur untuk menyeduh teh. Mungkin dengan ini pusing di kepalaku bisa reda.
Aku berjalan menuju balkon dengan tangan menggenggam secangkir teh hangat. Langit jingga mulai takluk pada warna biru tua. Beberapa bangunan sudah menyalakan lampu menandakan gelap segera tiba. Aku memposisikan kedua lenganku di atas pagar pembatas dengan sesekali menyesap teh dari gelas yang ku pegang.
Aku melirik arloji. 20.15.
Sebentar lagi Mas Fahri pulang. Aku melihat orang berlalu-lalang di bawah sana dari posisiku di lantai empat. Rue—jalan, Viala masih nampak ramai dengan aktifitas orang-orangnya, begitu juga Jalan Republik di sebelah kananku yang sepanjang jalannya banyak ditemui berbagai macam toko, mulai dari sepatu hingga tas. Mungkin lain hari aku berbelanja di salah satu toko itu.
Aku suka melihat kondisi jalanan yang didominasi manusia, bukan mesin. Aku juga suka bagaimana orang-orang di sini dapat berjalan dengan tenang di trotoar tanpa harus khawatir mendapat teguran dari pengendara motor yang mencoba mencari ‘jalur alternatif’ akibat dari jalan utama yang sesak.
Aku teringat ketika aku sedang berjalan santai di daerah Sudirman. Kala itu aku sibuk dengan ponselku dan hanya sesekali melirik ke depan untuk memastikan tidak menabrak siapapun. Aku yang juga menggunakan earphone tiba-tiba terdengar bunyi nyaring secara samar. Lalu ku lepas satu earphone ku dan suara nyaring itu semakin memekakkan telinga. Aku berbalik arah dan mendapati pengendara motor dengan wajah geram terus menekan klakson.
“Woy Mbak! Budek ya? Minggir, gua mau lewat!”
Lah? Siapa lo berani nyuruh gue buat menepi dari trotoar? Argh, ingin berkata kasar! Umpatku kala itu, dalam hati.
Aku memberinya jalan. Saat ia tepat melewatiku, ia menoleh dan memberi tatapan yang entah aku artikan apa, mungkin ‘nah gitu dong dari tadi kek’ yang aku balas dengan pandangan sinis.
Melihat kondisi di sini tidak seperti di Indonesia, sepertinya aku bisa merasakan menjadi pejalan kaki seutuhnya yang belum pernah aku rasakan di Jakarta.
Berbicara mengenai Jakarta dan Indonesia, pikiranku langsung merujuk satu nama; Andre. Andre apa kabar ya? Sekarang di Indonesia pukul tiga sore, hmm mungkin ia sedang bersiap menunaikan ibadah shalat ashar. Andre nyariin aku nggak ya? Kalau iya, mungkin segala cara ia usahakan untuk mencari keberadaanku. Kalau enggak, ah, aku nggak yakin dengan satu itu. Aku jahat ya, Ndre, udah ninggalin kamu gitu aja tanpa kejelasan? Bahkan tanpa sempat mengucapkan selamat tinggal. Aku bahkan mempertanyakan ulang keputusanku, ini demi kebaikan kita, atau hanya aku? Aku nggak tahu, Ndre, sekarang aku merasa udah gila karena pikiranku terus berbicara mengenai ini.
“Kalau melamun terus di situ, nanti bisa kesambet loh.”
Aku menoleh. Mas Fahri.
Aku memutar badan, punggungku bersandar pada pagar pembatas. “Barusan pulang, Mas?”
“Enggak sih, 5 menit lalu kayaknya, ngeliatin kamu bengong dulu,” ucapnya sambil menaruh kotak hitam di atas meja depan televisi. “Sini, La, makan dulu. Pasti belum makan, kan?”
Benar. Perutku berontak mendengar kata ‘makan.’
Aku mendekat ke sofa tempat Mas Fahri duduk. Aku tertegun ketika melihat meja penuh dengan sushi. California rolls dengan tepung ayam dan udang, salmon rolls yang menggiurkan, lalu ada yang dinamakan rouleaux de printemps, semacam lumpia yang di dalamnya terdapat udang, wortel hingga sayuran namun dengan kulit yang lebih tipis cenderung transparan. Kemudian ada sushi yang di bagian atas dan bawahnya terdapat kiwi untuk makanan penutupnya.
“Mas, ini kita nggak lagi ngadain syukuran seapartemen, kan?”
Ia menatapku sejenak, lalu terbahak.
“Ini bukan porsi kamu ya? Désolé alors. Semisal nggak habis, ditaruh kulkas aja buat besok sarapan, maaf ya sekali lagi.” Aku memaklumi. Mas Fahri belum tahu banyak tentang aku—makanan kesukaanku, hobiku, apa yang aku benci, termasuk ini, seberapa banyak kapasitas makanan yang mampu masuk ke lambungku. Aku nggak takut gemuk, bahkan aku sering makan tanpa mengkhawatirkan kondisi perutku, tapi ‘sering’ bukan berarti porsinya ‘banyak’, untuk kasus ini...just too much.
Beda cerita kalau Andre yang menyodorkan makanan sebanyak itu untukku, aku nggak berani jamin esok hari keberadaannya masih eksis di dunia ini.
Aku memegang sumpit dan mengambil satu yang menurutku paling enak. Aku lahap satu itu. Enak. Aku ambil yang lain. Enak juga. Sumpitku bergerak ke arah lain. Ini juga enak. Coba yang di sebelah sana. Sial, enak. Bahaya kalau terus begini.
Tanpa kusadari Mas Fahri ternyata belum mengambil satu makanan pun. Ia terpaku menatapku sambil menahan tawanya.
“Mas, jangan diliatin gitu ah.” Aku menaruh sumpit di meja, melirik ke arahnya sambil mengunyah dengan tanganku ku tempatkan menutupi mulutku.
“Tadi shock liat porsinya, sekarang malah kayaknya kamu yang mau ngehabisin sendiri.”
“Abis enak. He he he he he he he he,” kataku malu-malu. “Beli dimana sih ini, Mas?”
“Sushi Ball di Saint-Etienne, nanti kapan-kapan kita makan di sana.”
Aku terdiam sejenak. “Saint-Etienne, Mas? Bukannya itu jauh ya?”
Mas Fahri menepuk keningnya. “Bukan kotanya, di dekat sini ada Jalan Saint-Etienne, tadi sekalian lewat kok, La.”
“Oooooh, kirain, he he he,” tawaku canggung.
Akhirnya 3/4 porsi sushi tadi masuk dengan penuh penyesalan ke dalam perutku. Setelah tak ada suhsi tersisa rasa bersalahku muncul melihat Mas Fahri hanya makan sedikit padahal seharusnya ia yang banyak makan setelah seharian bekerja. Aku meminta maaf berkali-kali, sungguh, yang tadi itu khilaf, Mas Fahri berkata tak apa sama banyaknya.
Oh ya, aku belum berbicara tentang Mas Fahri, pria yang baru menginjak usia kepala tiga, yang berarti sama dengan Mbak Aya yaitu berjarak 7 tahun denganku. Rambutnya hitam bergelombang dan mempunyai lesung pipi yang tertanam di kedua pipinya. Raut wajahnya keras menggambarkan ia seorang tegas padahal hatinya lembut. Ia lulusan Universitas Sorbonne di Paris dan kini bekerja sebagai akuntan di Marseille.
Sewaktu di pesawat aku pernah menanyakan hal ini padanya. “Mas, kenapa kerja di Marseille tapi tinggal di Avignon? Aku ngeliat di Google Maps jaraknya satu jam perjalanan. Apa nggak capek?”
Dia menatapku, nampak ragu untuk menjawab pertanyaan tadi. Namun akhirnya ia menjelaskan kalau sedari masa kuliah dulu ia ingin tinggal di Avignon bersama Florencia, mantan kekasihnya yang berkebangsaan Belanda. Ia jatuh cinta dengan Avignon sewaktu liburan musim panas tahun ketiga ia di Sorbonne. Mas Fahri suka suasana abad pertengahan yang menjadi ciri khas dari Avignon. Banyak kastil masih berdiri dengan angkuh menampakkan kegagahannya telah merebut hatinya. Sejak saat itu Mas Fahri dan Florencia menetapkan bahwa Avignon adalah tujuan akhir mereka.
Setelah menabung pada masa awal-awal bekerja di Paris, ia akhirnya sanggup membeli satu apartemen sederhana di Rue Viala, yaitu apartemen yang kami tempati sekarang. Lalu ia pindah ke satu kantor yang bertempat di Marseille--sampai sekarang, sedangkan Florencia sempat bekerja di biro hukum di Avignon. Ia tak keberatan dengan perjalanan super pagi, dan pulang malam hari. Karena tinggal di Avignon adalah keinginannya, jadi ia tak merasa itu sebuah masalah besar.
“Awalnya sih kerasa banget capeknya, La, tapi mungkin karena udah terbiasa, jadi rasa capek di perjalanan udah nggak kerasa banget kayak dulu.”
Aku mangut-mangut. Berhubung dia menyinggung tentang Florencia, aku turut penasaran dengan kisah mereka. Mas Fahri garuk-garuk bagian belakang kepalanya mendengar keingintahuanku.
“Yaaa, we broke up, La, gimana lagi? Dia nggak habis pikir sama pikiran orang tua aku yang dengan mudahnya mengakhiri hubungan kami yang udah bertahun-tahun. Bahkan kalau masalahnya agama, Floren udah bersedia untuk pindah. Akhirnya dia blame aku karena aku nggak bisa nolak keinginan Mama, dia ngira aku udah cinta mati sama kamu jadi dia berpikir itu bukan maunya Mama, tapi mauku,” ia menghentikan kalimatnya untuk menarik nafas sejenak. “Yaudah, kita berantem hebat, putus dan dia milih pulang ke Belanda. Jujur, aku stres, La, karena kita pacaran udah lama tapi harus berakhir dengan seperti ini.” Roman wajahnya menunjukkan kesedihan yang nyata. Saat itu juga, Andre melintas dipikiranku. Dan mungkin kondisi apartemen yang sangat sangat berantakan itu tak lepas dari masalah yang Mas Fahri alami sendiri.
“Kamu sendiri gimana, La?” Aku tersentak.
“Kalau nggak salah, bukannya kamu juga punya pacar ya? Artis, kan?” Ia bertanya lagi.
“Iya, Mas, tapi...,” aku ragu untuk mengatakan itu.
“Tapi?” Nada bicaranya agak ditekan dan ia menaikkan satu alisnya.
Aku menarik nafas panjang. Sepertinya perjalanan panjang di udara saja masih belum cukup menguras tenagaku.
“Aku nggak seperti Mas, aku pergi tanpa pamit.” Itu dia. Kalimat pertama sudah dilontarkan, kalau sudah begini maka harus kuteruskan.
Tak ada perubahan ekspresi pda roman Mas Fahri. Aku melanjutkan kisahku.
“Aku terlalu pengecut untuk bilang mengenai ini sama Andre.” Aku melengos, menatap kabin pesawat memerhatikan pramugari yang sibuk menawarkan makanan kepada tiap penumpang.
Selesai mendongeng timbul perasaan lega. Aku merasa seperti curhat dengan Mbak Aya, mungkin faktor kesamaan umur diantara mereka berdua yang menjadikan aku nyaman dengannya. Sejak saat itu aku dan Mas Fahri lebih condong ke abang-adik daripada suami istri.
---
Hari-hari berikutnya di Avignon aku gunakan untuk menyisiri tiap sudut kota ini. Aku mengunjungi berbagai tempat, diantaranya Palais des Papes, sebuah istana peninggalan abad pertengahan yang terdiri dari balai kota hingga teater. Berada di tengah halaman istana seakan menarik ragaku mundur ke ratusan tahun lalu menuju masa dimana Paus Benedict III mulai membangun istana sebagaimana yang terpampang di hadapanku ini. Aku takjub melihat bagaimana megahnya dua belas tower batu yang melintangi istana ini. Kemudian di lain hari aku pergi ke Pont d’Avignon, jembatan abad pertengahan yang terkenal di barat laut pusat kota Avignon. Jembatan ini membentang di atas sungai Rhône dan memiliki panjangnya sekiar 900 meter. Aku datang pada sore hari ketika langit nampak keemasan memamerkan keindahannya, berada di sini tanpa mengunggah fotoku ke media sosial sungguh menyiksa.
Namun dari beberapa tempat yang aku kunjungi, aku punya dua lokasi yang menjadi destinasi favoritku. Pertama Rocher des Doms, taman yang terletak di utara Avignon. Di salah satu sudut taman ini terdapat pohon pinus yang berjejer rapih. Rerimbuan pohon menjadi nilai plus karena membuat suasana menjadi sejuk. Tidak jauh dari deretan pohon itu terdapat bangku taman yang biasa aku hampiri untuk menulis atau duduk sembari menyantap makanan ringan melihat orang-orang menikmati harinya.
Kedua ialah Rue des Teinturies, sebuah surga kecil di Avignon. Jalan ini dipenuhi berbagai restoran, kafe hingga teater dan di sisi satunya mengalir sungai Sorgue, yaitu sungai kecil yang di ujungnya terdapat kincir air yang menambah kesan pedesaan di jalan ini. Pohon rimbun sepanjang jalan ini menambah kesan nyaman ketika hendak menyusuri Rue des Teinturies. Aku senang duduk di pembatas batu tepi sungai Sorgue dekat kincir air dengan laptop terbuka di pangkuanku. Biasanya aku menulis sembari mengenakan earphone untuk mendengar lantunan musik akustik, namun kala duduk di sini, telingaku terbuka lebar mendengarkan gemericik air yang secara tak langsung menjadi lagu latar bagi jari-jariku menari di atas keyboard.
Setelah menelusuri kota ini, aku menjadi paham mengapa Mas Fahri memilh Avignon sebagai tempat tinggalnya. Mengapa ia rela bolak-balik ke Marseille dan tidak menetap di sana. Aku mengerti setelah kakiku melangkah lebih jauh, mataku menatap lebih banyak, dan hatiku merasakan lebih dalam keseluruhan dari kota ini.
“If you are coming to visit Provence, don't stop in Avignon! Once here, like a siren, the city will entrance you and you won't want to leave!”
Aku merasakan hal yang sama seperti yang Mas Fahri rasakan.
Aku jatuh cinta dengan kota ini.
Namun aku di sini bukan bersama orang yang aku cintai.
I wish you were here, Ndre.
to be continued