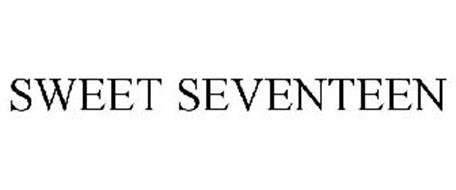Chapter I-VII bisa dilihat pada tag series.
---
Andre
Ndre, i was married...
Satu kalimat singkat yang masih melekat dipikiran gue hingga detik ini. Apa yang ia katakan setelahnya gue anggap sebagai remeh temeh belaka. Namun mengetahui bahwa ia pernah menikah? What the fuck...gue sama sekali nggak pernah terbayang mengenai hal ini. Bahkan pikiran busuk gue kalau ia menjadi korban pembunuhan dan jasadnya tak pernah ditemukan terdengar lebih masuk akal dibanding dengan kenyataan bahwa ia pernah menikah dengan...dengan seorang cowok yang bahkan nggak pernah ada di lingkaran hidupnya.
Ah...anjing.
“Aku begini karena terpaksa, Ndre...,” persetan.
Mungkin alasannya dapat diterima jika ia bercerita dengan orang yang secara langsung tidak terlibat dalam skenarionya. Huh, skenario...berarti penuh dengan kebohongan. Tapi alasan itu nggak dapat gue terima. Oleh pikiran gue. Oleh hati gue. Karena di sini gue berperan sebagai tokoh utama, atau lebih tepat; seorang main character yang nggak tau akhir dari peran yang ia jalani.
Seandainya ia berkata jujur sejak dulu, mungkin gue secara sukarela mundur dari kehidupannya. Terdengar begitu mudah. Atau mungkin dikarenakan sekarang gue menghadapi kondisi yang jauh lebih buruk daripada itu, sehingga apa yang tadi gue katakan terdengar mudah dilakukan? Entahlah. Tapi yang pasti, ditinggalkan tanpa alasan dan datang kembali membawa alasan tersebut itu sungguh menyakitkan.
“Tuh kan, Yan, ini anak nggak bisa ditinggalin sendirian sekarang. Takut gue.”
“Iya, gue juga khawatir...hoi, bangun!”
Gue tersadar ketika Dian menyetakkan jarinya tepat di muka gue. “Eh, sorry,” ucap gue menyadari makna tatapan ‘tuh kan’ teman-teman gue.
“Tuh kan...gue bilang juga apa. Lagi rame begini aja masih bisa bengong, gimana kalau sendirian. Setan juga kayaknya capek mau masuk ke badan dia,” Rama yang duduk berhadapan dengan gue menghembuskan asap rokoknya ke langit-langit.
“Ndre, nggak usah terlalu dipikirin, okey? Sekarang lo lagi sama kita-kita, lupain sejenak pembicaraan lo sama Laila tempo hari,” tangan Dian menepuk bahu gue dan menatap gue dengan tatapan keibuan khas dirinya.
Gue mengangguk perlahan. Gue nggak mau ngerepotin mereka lebih jauh lagi. Meskipun gue sedikit kurang suka saat Dian menyebut nama itu. Nama yang kini berusaha gue hapus dari memori gue.
Namun tak kunjung bisa.
“Eh, waiters di sini cakep juga. Jomblo nggak yah dia?” disaat Rama dan Dian mengkhawatirkan gue, Richard terpaku memandang seorang wanita dibalik mesin kasir.
“Si kampret malah ngeliatin anak orang lagi. Di sebelah lo itu loh ada teman kita yang lagi bermasalah. Fokus woy!” segepal tisu lemparan Rama mendarat tepat di muka Richard.
“Gue udah kesambet sama senyumnya doi, Ram...nah...nah, dia ngeliat ke arah gue kan!” tubuh Richard bergoncang kegirangan dan secara tak sadar ia menepuk bahu kiri gue berulang kali.
“Itu karena dia ngerasa diliatin sama orang freak, bego! Lo ngeliain dia lima menit lagi juga dia minta resign ke bosnya,” balas Rama.
“Biarin kali, Ram, Richard kan punya masalahnya sendiri. Kasihan juga dia udah lama nggak punya gandengan.” Gue menangkis tangan tepukan Richard dari bahu gue karena mulai merasa anak ini sengaja mau nyakitin gue.
“Loh, kata siapa udah lama nggak punya gandengan? Bukannya baru 3 bulan lalu, ya? Tapi...” Rama menahan kalimatnya.
“Tapi nggak taunya si cewek agen MLM yang lagi nyari korban baru,” timpal Dian cepat, membuat meja kami menjadi penuh oleh tawa.
“Bangsat kalian semua ya,” geram Richard.
“Love you too, Chard,” Rama masih terpingkal. Karena menghina Richard adalah salah satu hal yang ia sukai--selain tidur dengan wanita tentunya.
Berada di antara mereka membuat gue bisa sedikit melupakan pertemuan itu. Pertemuan pertama gue dengannya dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Meskipun bayang-bayang malam itu kerap melintas dipikiran gue. Jujur, gue berharap bisa masuk ke bagian hipokampus di otak gue untuk membuang memori akan pertemuan itu. Enggak...mungkin memori gue secara keseluruhan dengan dia. Sial, bahkan sekarang gue enggan menyebut namanya.
---
Setelah sekian lama, gue kembali lagi ke sini. Kota penuh cerita akan masa kuliah gue dulu. Kota dimana gue bertemu dengannya, kemudian mulai merajut mimpi bersama serta saling mengisi kehidupan satu sama lain.
Gue sebetulnya bisa saja menolak manggung di acara clothing festival yang baru saja diselenggarakan. Teman-teman pun bahkan sampai menanyakan ketersediaan gue untuk menerima tawaran ini. “Yakin lo, Ndre, mau main di Jogja?” Dian memastikan berulang kali dan gue iyakan berulang kali pula.
Seperti yang telah gue katakan, gue nggak mau ngerepotin sahabat gue, terutama jika sudah masuk ranah band. Meskipun gue punya alasan untuk menolak tampil di sini; gue kurang suka sama set-list acaranya. Dimana Alchemy tampil setelah Raisa dan sebelum DJ Una. Random abis. Entah kenapa gue pribadi kurang sreg kalau berada satu panggung dengan musisi lain yang genre musiknya saling berbeda. Tapi gue nggak pernah mengungkapkan hal ini. Selama personil lain dan Dian setuju, gue memilih untuk diam dan mengikuti saja.
Pada hari H, gambaran gue tentang acara itu menjadi nyata; dede gemesh penggemar Raisa mundur untuk kemudian digantikan segerombolan anak muda dengan pakaian serba hitam yang segera membentuk circle pit dan mosing ketika musik kami bergema. Setelah kami selesai mereka mundur dan digantikan oleh kelompok anak muda lainnya untuk sama-sama mengangkat tangan ke udara sambil geleng-geleng kepala mengikuti flow musik yang naik turun. Asli..random.
“Itu penggemarnya Raisa nggak usah mundur! Kita mau bawain album Raisa versi rock!” teriak Rama di atas panggung. Penonton tertawa. Gue geleng-geleng kepala.
---
Sebetulnya gue enggan singgah terlalu lama, tapi Dian dan Bram ingin sedikit nostalgia dengan Jogja. Rama mengatakan ia juga butuh jauh-jauh dari Serang. Sedangkan Richard ingin mencari pacar di Jogja. Gue yang tak ingin merusak keinginan mereka memutuskan untuk diam.
Maka di sinilah kami, bercengkrama di sebuah coffee shop di daerah Pogung. Hanya Bram yang tidak ikut karena ia mengunjungi pacarnya yang notabene merupakan adik tingkat Bram semasa kuliah dulu.
Jogja adalah kota romantis. Itu sudah hakekatnya. Namun pandangan gue terhadap kota ini agak melenceng dari semestinya. Jogja dan kenangan seperti sudah tak bisa dipisahkan. Dan kenangan, adalah musuh terbesar gue saat ini.
Bagi gue sekarang, Jogja merepresentasikan kesedihan.
Aspal jalanannya menyimpan jejak langkah gue dan dia. Nafas kami yang pernah menyatu dengan udara sejuk Jogja malam hari. Tiap elok jalanannya yang pernah kami sanggahi untuk memastikan kebenaran sisi romantis Jogja--dan kami berbagi tawa saat itu.
Ah, anjing! Kenapa gue jadi sentimen gini sih?
“NDRE!”
Gue tersentak.
“Belum lama setelah bengong pertama, sekarang malah kambuh lagi,” kata Rama.
“Apa kita pulang aja? Mungkin lo emang lagi belum bisa ada di kota ini lagi, Ndre,” Richard menambahkan sembari menyeruput kopinya.
Gue mengambil bungkus rokok di hadapan gue, lalu menyulutnya. “Nggak usah, Chard. I’m okay, kok.” Gue mencoba tersenyum meyakinkan mereka.
“Kan, tau gini tadi kita ke Liquid aja,” ujar Rama.
“Ogah.”
“Kenapa? Masih nggak mau mengunjungi tempat yang ada alkoholnya?” balas Rama dingin.
“Lo tau sendiri gue gimana,” gue berujar singkat. Gue memang bukan peminum. Bahkan untuk mengunjungi tempat yang menyediakan alkohol gue kerap menolak.
“Iya, justru karena gue tau lo gimana makanya gue ajak ke sana. Yang gue tau, Andre yang sekarang itu cuma cowok melow yang dengan mudahnya melanggar prinsip yang selama ini dia pegang.” Gue menatap nanar ke sembarang arah, namun gue tau kalau Rama melayangkan pandangan tajam pada gue.
“Yang gue tau, Andre itu juga anti sama rokok dan selalu menolak kalau disodorkan rokok bahkan dengan kita-kita. Bukan orang yang dengan kesadaran penuh mengambil sendiri bungkus rokok di hadapannya yang bahkan bukan miliknya...” Rama menahan kalimatnya. Gue masih belum melihat ke arahnya. “So, nggak nutup kemungkinan kalau Andre yang seorang anti alkohol pun bakal ikut minum saat berada di lingkungan yang mendukung.”
“Ram, udah.” Dian membuka suara. Terdengar berusaha menenangkan seperti semestinya.
“Huh, bangsat...lo nggak tau gimana rasanya aja,” sebuah kalimat meluncur begitu saja dari mulut gue.
“Gue tau...”
“Lo tau karena dia udah cerita ke lo duluan, gitu? Biar lo bisa ada dipihak dia dan ngeyakinin gue untuk balik lagi sama dia? Iya?” Gue menatap Rama. Rama tercengang ketika gue memotong ucapannya. Tergambar raut keheranan pada wajahnya ketika mendengar perkataan gue. Namun dalam sekejap ia bisa kembali menguasai ekspresi wajahnya dan kembali menunjukkan tatapan elang miliknya pada gue.
“Maksud lo apa?” ujarnya dingin.
“Lo jadi orang pertama yang dia pilih buat diajak bicara. Hahahaha. Lucu. Dan lo nggak ngasih tau ke gue tentang pertemuan itu,” gue mengalihkan pandangan lagi. Richard dan Dian tampak khawatir dengan aura ketegangan yang semakin terasa diantara kami.
“Kok jadi ke gue?” Rama meninggikan nada bicaranya. Rokok yang masih setengah dalam jepitan jemarinya pun ia gerus. Gue tau, kalau ia sudah begini, berarti ia tengah kesal dengan lawan bicaranya.
Gue melempar senyum sinis. “Karena lo seakan membenarkan apa yang telah dia lakukan terhadap gue. Atau mungkin selama ini lo turut berkomunikasi diam-diam sama seperti Nadine yang juga membohongi gue?” ada perasaan aneh yang menyelimuti gue. Ada emosi yang ingin gue luapkan. Gue tau ini salah. Gue sadar apa yang terlontar dari mulut gue adalah sebuah kesalahan besar. Tapi semuanya keluar begitu saja tanpa merasa bisa ditahan.
“Tai lo, Ndre,” Rama bangkit dari duduknya. “Lo yang sekarang bukan lo yang gue kenal sebagai sahabat gue. Ini semua masalah lo dengan masa lalu lo. Ini semua tentang ego lo yang menolak menerima kenyataan. Ini semua mengenai kebebalan hati lo sehingga mulai menyalahkan sekitar lo!” Ia mengacungkan telunjuknya ke arah gue. Suaranya meninggi mengakibatkan kami menjadi fokus bagi pengunjung lain. Terlihat para barista saling berbisik, mungkin bingung bagaimana harus bersikap kepada kami. Dan beruntung malam sudah larut sehingga tempat ini tidak seramai beberapa jam lalu.
“Anjing. Mood gue rusak di sini. Gue cabut duluan,” Rama bergerak meninggalkan kami. Tak ada satu pun dari Dian atau Richard yang menahannya.
“Duh...kok jadi gini sih...,” Richard mengusap keningnya yang berkerut, sedangkan Dian seakan tercekat dan tak mampu mengeluarkan sepatah kata dari mulutnya. Gue tau, gue telah membuat runyam keadaan. Gue tau bahwa gue salah. Tapi entah mengapa gue enggan mengakui ini sebagai salah gue.
“Sorry udah buat chaos,” gue mendengus. “Gue cabut duluan juga ya. Maaf sekali lagi.” Gue beranjak sebelum ada respon dari Dian dan Richard. Gue memutuskan untuk kembali ke hotel yang berada di jalan Margo Utomo.
“Maaf ya, Mas, Mbak, Ded, udah ngebuat sedikit keributan di luar.” Gue juga meminta maaf kepada barista dan pemilik kedai saat berpapasan.
---
Setiba di kamar gue terduduk di tepi ranjang dengan kepala merunduk. Mengutuk kebodohan yang baru saja gue perbuat. What the hell happened to me? Kemana Andre yang biasanya, Ndre?
Berada dikesendirian memaksa memori terbang kembali ke malam itu. Satu malam ketika Kronology Coffee disanggahi tamu mengejutkan. Tamu yang sejujurnya dinanti, tapi bukan dengan cara seperti ini.
“Selamat datang, Kak, silahkan mau order apa? Kebetulan kita sudah last order ya, Kak,” terdengar Alika mengucapkan kalimat sambutan pada pelanggan yang baru datang. Gue yang sedang merapikan barang dan melakukan cek beberapa inventory di ruang belakang segera melirik arloji. “Gila, orang ini nggak tau atau sengaja nih baru datang jam 11?” gue menggerutu. Jujur, gue kurang suka jika mendapat pelanggan yang datang menjelang closing time kafe.
Gue masih disibukkan dengan kegiatan gue sehingga tak sempat melirik ke luar untuk memastikan siapa yang datang. Karena biasanya pelanggan yang datang selarut ini merupakan segerombolan anak muda atau mereka yang biasa disebut ‘pendekar kopi’ di kota ini.
Cukup lama tak terdengar adanya transaksi di kasir sebelum...ah! Wangi ini...gue hafal dengan wangi parfum ini. Wangi parfum yang terakhir kali masuk melewati cuping hidung gue dua tahun lalu. Gue masih meneruskan apa yang sedari tadi gue lakukan, meski dengan perasaan gelisah dan tangan yang mulai gemetar.
“Aku order Laila Speciality.” Gue berhenti seutuhnya mendengar suara itu. Suara lembut itu. Tubuh gue mendadak kaku. Tremor di tangan gue semakin jadi. Jantung gue berdegup lebih cepat. Nggak salah lagi...itu pasti dia.
“Eng...maaf, Kak, kita nggak ada menu itu,” tentu nggak ada, Alika. Nggak ada satu pun yang tau menu itu selain gue dan gue nggak pernah mengumbar mengenai kisah cinta masa lalu gue selain kepada sahabat-sahabat gue.
Laila speciality...sebuah menu imaji yang pernah gue ucapkan ketika kami terlibat pembicaraan sore hari penuh canda tawa di teras kos gue dulu. Sebuah kolaborasi antara pisang goreng, kopi tubruk, senja dan dia yang membuat sore itu menjadi sempurna.
“La, nanti di kafeku akan ada menu dengan namamu sebagai bagian dari signature drinks. Sekaligus, membawa sebagian dari kamu bersemayam di sana,” senyum gue padanya kala itu sambil menyeruput kopi tubruk.
“Hmmm, mulai deh gombalnya si Bapak. Lagian kayak aku udah mati aja pakai kata bersemayam segala,” sahutmu dengan senyum indah itu. “Lagian emang signature drink gimana coba?” kamu melanjutkan.
“Belum kepikiran sih, La. Mungkin campuran velvet sama espresso gitu. Kamu suka velvet dan aku tetap menggunakan base kopi. Cocok nggak?”
“Enggak!” kamu menyumpalkan sepotong pisang goreng ke mulutku sembari menampilkan ekspresi menggemaskan. Tentu siapa yang bisa kesal jika kamu menunjukkan wajah menggemaskan itu?
Ah, good old days.
Kembali ke malam itu, setelah menyuruhnya duduk, gue mulai membuat pesanan. Alika dan para barista gue memerhatikan gue dengan ekspresi heran sekaligus bingung.
Laila Speciality telah berada di atas baki. Akan tetapi gue masih terpaku menatap minuman berisi red velvet, kopi dan kenangan ini.
“Bang? Ini aku serve sekarang?” pertanyaan Alika menyadarkan gue.
“Nggak usah, Ka. Kali ini biar aku yang ngantar,” gue coba menciptakan senyum senatural mungkin. Raut wajah Alika tak berubah, seakan masih menyimpan berbagai pertanyaan yang menunggu waktu untuk diutarakan.
Gue menghela nafas. Mencoba menghadapi sosok nyata dari bagian diri gue yang hilang dua tahun lalu. Gue bahkan belum saling melempar tatap dengannya, gue hanya baru berjumpa dengan wangi parfum dan suara lembutnya saja.
Langkah gue sempat terhenti ketika gue secara langsung melihat sosoknya duduk membelakangi pintu kaca di bagian smoking area kafe. Rambutnya kini dipotong pendek. Gue membawa kaki yang kian berat melangkah menuju meja itu. Semakin dekat, tangan gue semakin bergetar.
“Here’s your coffee,” adalah kalimat pertama gue kepadanya setelah dua tahun berlalu. Kali ini jarak gue dengannya begitu dekat. Wangi tubuhnya pun semakin menusuk indra penciuman gue. Dan diantara kami ada kenangan yang menyeruak ke udara.
Saat itu pula gue kehilangan kendali. Air mata itu tak tertahankan. Gue benci dengan air mata, karena ia dapat keluar sesukanya disaat kita tidak menginginkannya. Gue mencoba tegar, tapi semakin gue mencoba, maka kerapuhan gue semakin tampak.
Malam itu, ia menceritakan segalanya. Merobohkan dinding besar yang selama ini membatasi kami. Dari masa lalunya yang tak pernah ia bagi kepada gue, hingga kehidupannya berumah tangga dengan seorang pria lain dan tinggal di suatu daerah di Prancis selama dua tahun menghilang bak ditelan bumi. Dan memang pantas tak ada kabar, Prancis, bro, haha, siapa yang nyangka? Tolol banget gue nyangka dia mati.
Tak pula banyak kata yang gue ucapkan. Gue lebih banyak terdiam menatap kosong ke berbagai arah dengan telinga terbuka lebar mendengar kebenaran yang menyakitkan.
“Sudah hampir pagi, sebaiknya kita pulang,” gue berdiri dari kursi dengan pandangan melayang ke lantai.
“Ndre...,” gue mengindahkan panggilannya dan mulai melangkah keluar. Mau tak mau ia mengikuti gue untuk menyudahi pertemuan menyakitkan ini.
Sudah sebulan sejak gue bertemu dengannya, tak ada hari tanpa memikirkan malam itu. Gue bingung bagaimana harus bertindak selanjutnya. Sosok yang gue rindukan kini telah kembali, tapi ia sekarang tidak sama dengan ketika ia pergi dahulu. Ada lubang besar yang terbentuk dan sulit untuk ditutup kembali.
“Ndre?” Rama melongok dari balik pintu kamar.
“Eh, Ram, masuk.”
“Lo nggak apa-apa?” gue mengangguk lemah.
“Gue minta maaf soal tadi. Gue juga nggak tau kenapa gue jadi sensitif kayak cewek gini,” ujar gue malu.
“Iya, geli gue kita marahan kok kayak cewek. Mending adu pukul sekalian daripada bentak-bentakan doang,” Rama berdiri bersandar pada dinding di dekat gue.
“Yaudah hayu berantem biar gentle dikit,” gue lirik Rama sambil tersenyum.
“Nggak lah, bisa dibantai gue sama lo. Badan gue kurus gini,” gue terkekeh. “Maaf juga tadi gue udah buat malu ngomong segitu kerasnya di tempat umum.”
“Gimana rasanya, Ram? Nggak enak, kan? Tadi itu lo baru pertama ya ngomong dengan nada tinggi di depan umum dengan kesadaran penuh?”
“Hehehehehe, jadi gitu yah rasanya, mending nggak sadar sekalian deh,” Rama menggaruk bagian belakang kepalanya. Bukan hal baru kalau ia sering meracau di tempat umum. Tapi jika ia begitu tanpa pengaruh alkohol, kejadian di coffee shop tadi adalah yang pertama.
“Anjing, nggak gitu juga,” kami tertawa.
---
Gue dan Rama menghabiskan malam di pekarangan hotel dengan berbungkus-bungkus rokok dan beberapa gelas kopi. Benar kata Rama, ini hanya masalah gue dengan masa lalu gue dan apa yang akan gue lakukan untuk masa depan gue. Saat ini seakan semuanya menjadi satu; masa lalu, kini dan esok.
Dan sekarang, bergantung pada bagaimana tindakan gue menghadapi situasi pelik ini.
Memafkaan meski sulit?
Atau
Melepaskan?
to be continued