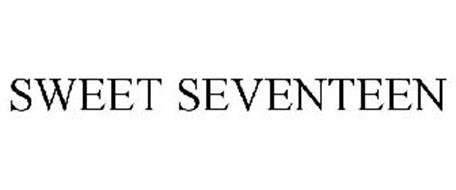|
| jingganyasenja.files.wordpress.com |
Pagi itu, suatu pagi akhir pekan yang biasa. Pagi yang menghantar rasa lelah ke persembunyiannya setelah ditempa berbagai kesibukkan. Rasa lelah yang lusa esok, ia akan kembali melengkapi hariku dan jutaan orang lain di bumi.
Aku terbangun ketika jam wekerku berbunyi pada pukul lima kurang lima belas menit. Aku beranjak dari tempat tidur, lalu duduk tertunduk di tepi ranjang dan mulai menghembuskan nafas secara perlahan. Sebuah pagi baru telah menyambutku, tapi tidak dengan kenangan pahit yang tak kunjung hilang.
Ku bawa langkah yang terasa berat ini menuju kamar mandi. Mengambil wudhu tuk bertegur sapa dengan Sang Pencipta. Bersyukur karena masih diberi kesempatan kasih untuk kembali menghirup udara segar pagi hari.
Rutinitas pagi hari akhir pekan ini diakhiri oleh membuat sebuah kopi dengan tanganku sendiri. Satu brewing machine sengaja aku pindahkan dari toko ke dapur rumah dengan hasil jerih payahku sendiri. Bukankah seseorang rela berkorban demi hal yang ia sukai? Seperti membeli barang kesukaan yang memerlukan pengorbanan material, atau... Mendapatkan cinta idaman dengan mengorbankan hidupmu, waktumu.
Secangkir Flores Bajawa kini ada digenggaman, menemani ragaku yang bergerak menuju halaman belakang rumah dan menyapa penghuninya. Tanaman yang dulu kamu rekomendasikan untuk rumah kita, rumahku. Ku geser pintu kaca yang membatasi ruang utama dan halaman belakang dan seketika udara segar merangsek memenuhi paru-paru. Udara ini membuat tubuhku hidup, tapi sumbernya mematikan perasaanku.
Kubiarkan pupilku beradaptasi dengan sekitar. Kabut tipis masih nampak menyelimuti dan kemana Matahari? Ah, nampaknya ia bangun sedikit terlambat hari ini. Aku biarkan saja dia dengan tidurnya. Maksudku, ia seorang pekerja keras, bukan? Setiap hari memberikan tenaganya untuk miliaran orang di bumi, hanya sesekali ia terlambat karena ia harus bergantian dengan hujan yang tak punya jam kerja tetap. Tapi hari ini kelihatannya bukan harinya hujan datang dan Matahari belum menampakkan sedikit pun sinarnya. Ah, aku biarkan saja dia dengan tidurnya. Sedikit terlambat tidak apa-apa, aku rasa ia kelelahan.
Aku pejamkan mata dan kopi berpindah dari cangkir di tangan ke dalam perutku. Kubiarkan pahitnya menjalar sedemikian lambatnya. Menempel pada langit-langit mulut dan dinding tenggorokanku. Bukankah pahitnya secangkir kopi tak bisa dibandingkan dengan pahitnya kehidupan? Karena menurutku pahit yang terdapat pada kopi merupakan esensi dari kopi itu sendiri, sedangkan manis dan asamnya secangkir kopi hanyalah rasa pelengkap. Sedangkan kehidupan, apakah tujuan hidup seseorang adalah kepahitan? Aku pikir, itu hanya pelengkap dari makna hidup itu sendiri.
Tapi bagaimana dengan hidupku? Kenapa yang aku rasakan hanya kepahitan? Seakan kepahitan itu mengurungku dalam penjara keji dan tak memberikan kesempatan menghirup udara bebas. Udara kebahagiaan. Udara penuh kasih sayang. Bukan kegiatan dalam penjara yang menyesakkan. Duduk di sudut ruangan, pagi hari sarapan penyesalan. Siang (atau mungkin sore) bekerja menambang batu harapan. Menghancurkannya menjadi kepingan kecil. Dan malam, istirahat di bawah langit-langit gelap nan sempit. Bukan langit-langit penuh bintang di sebuah lahan penuh ilalang tinggi di atas atap mobil dengan kamu ada di sampingku.
Sekarang di sinilah aku, berdiri di halaman belakang rumah yang awalnya dirancang oleh dua orang, namun hanya ditempati oleh salah satunya. Kubuka mata dan kuhirup nafas dalam dan kembali menghembuskannya perlahan. Matahari memang sedang malas hari ini. Sudah tiga puluh menit melewati pukul lima dan ia masih belum menunjukkan sedikit pun tanda kehadirannya? Ia bahkan kalah dengan Roni, kenari kecilku yang suaranya meresap ke gendang telinga dengan nyaring, tapi begitu halus untuk didengar. Iya menyapaku, kubalas dengan senyum dan menyentakkan jari di depan kandangnya.
Mataku kembali menyusuri halaman belakang ini, mulai dari sudut kiri yang terdapat kolam ikan dengan sebuah jembatan kecil di atasnya yang berujung pada gazebo kecil tempat kita –aku, nantinya ngaso kala penat dengan hiruk pikuk kehidupan perkotaan. Lalu beralih ke bagian tengah dimana deretan pinus berukuran kecil tertanam, dan saat perlahan pandanganku mengarah ke bagian kanan, terdapat cahaya di sana. Tepat di sebelah daun pandan yang merupakan tanaman terakhir yang ditanam di sini.
Hey, Matahari? Itu kah kau? Akhirnya kau dat...
Tunggu.
Itu tidak nampak seperti engkau, Sang Surya. Lalu...
Ah! Senja?! Kenapa dia di sini? Maksudku, kenapa pada waktu ini? Bukankah ini belum waktunya ia menampakkan diri?
“Hai, Al.” Sebentar. Ia menyapaku? Ia tahu namaku?
“Eh, hai.” Aku menjawabnya canggung karena masih belum mengerti sebenarnya ada apa ini.
“Ada apa dengan dirimu? Tidak biasanya kau bertingkah seperti itu. Dimana ketenanganmu saat bertemu klien-klien besar? Sederhana lagi, dimana semua ketenanganmu itu saat kau bertemu denganku?” Aku diberondong pertanyaan olehnya. Membuatku semakin kebingungan harus menjawab dari mana. Namun kenyataannya, memang aku tidak bisa menjawabnya.
“Aku rasa mereka yang bekerja di dalam otakmu kini sedang kalang kabut. Mencerna dan mencari koneksi dari kejadian yang bahkan belum sepuluh menit terjadi.” Senja menambahkan.
Mendengarnya, aku mencoba membuka suara. “Dari mana kau tahu namaku?”
“Aku tidak hanya tahu namamu, tapi aku kenal siapa kamu,” Senja tersenyum. Aku terdiam. Menunggu apa yang ia akan katakan selanjutnya. Jujur, aku khawatir. Tapi aku penasaran. “Aku juga kenal seorang di Jepang sana yang kini sedang mabuk sake ditemani dua orang Geisha di sebuah kedai yang terletak di kaki gunung Gunung Arashi. Atau seorang pria yang sedang menikmati ganja maroko di sebuah cafe di pusat kota Rotterdam. Atau presiden negara adidaya yang sekarang ini sedang bermain golf indoor di ruangannya. Aku kenal dengan dirimu, seorang lelaki 30 tahun yang setiap empat kali dalam sepekan selalu menyisihkan waktunya untuk menikmati keindahanku.” Aku tercengang. Senja menjelaskan semuanya dan ia benar.
“Bagaimana bisa?”
“Kau sudah tahu jawabannya,” Senja kembali tersenyum ke arahku. Aku terdiam tidak mengerti. Senja menghirup nafas dalam dan menghembuskannya perlahan sembari menggelengkan kepalanya. “Sungguh kau tidak tahu?” Ia bertanya. Aku mengangguk pelan.
“Apa alasanmu kerap mengunjungiku?”
Alasanku mengunjunginya? Untuk sepersekian detik aku tak menjawab, sebelum bibirku bergerak mengatakan untuk mencari ketenangan dan menikmati fisiknya.
“Lalu, apa kau merasa tenang kala mengunjungiku?”
“Ya.” Aku menjawabnya tanpa ragu karena memang benar adanya. Entahlah, seakan goresan jingga di langit sana terlihat sungguh menenangkan.
“Kau tahu, Al? Saat orang-orang melihatku dengan tujuan benar-benar ingin melihatku. Merasakan kehadiranku. Mencari ketenangan melaluiku. Maka saat itulah aku menjadi satu dengan orang-orang itu. Aku masuk menuju relung jiwa orang-orang itu, sampai palung terdalam dimana kegelisahan itu ada. Dan pada saat itu juga aku mengenal mereka; siapa mereka, dari mana asalnya, bagaimana latar belakang keluarganya sampai hal terakhir yang mereka permasalahkan atau membuat mereka bermasalah. Hal demikian juga aku lakukan kepada dirimu, Al. Dari...,”
Senja terdiam. Ia menatapku sejenak kemudian mengalihkan pandangannya kembali menuju tanaman pandan yang berembun.
“Dari waktu-waktu indahmu menikmatiku bersama Tisya, sampai kesendirianmu yang coba kau isi dengan kenangan itu bersamaku.”
Aku tercekat. Dan bayangan itu seketika muncul. Muncul di waktu yang tidak aku inginkan. Maksudku, aku memang menyisihkan satu atau dua jam sehari selama dua tahun belakangan ini dengan Senja sebagai teman ‘melamunku’ untuk menyelami memori itu. Bagi seorang pria yang baru menyentuh kepala tiga, hal itu tentu menyedihkan.
“Indah, bukan?”
“Tidak lebih indah darimu.”
“Gombal.”
“Tapi suka, kan?”
“Enggak, jelek!”
“Terus kenapa senyum-senyum?”
“Gombal kamu garing.”
“Loh?”
“Garingnya aku suka, gombalnya enggak.”
“Aneh.”
“Tapi cinta, kan?”
Aku tersenyum. Begitupun ia. Di dalam mobil berwarna putih, di bawah cahaya jingga Senja yang menjadi saksi bisu dan deburan ombak merangsang gendang telinga untuk terus mendengarnya, we’re kissed.
Sial. Kilasan memori itu muncul tanpa diperintahkan. Tapi mengapa? Mengapa hanya berupa kenangan manis saja yang –entah siapa yang mengatur, yang kerap muncul? Maksudku, aku dan, eh, ehm.. Tisya, juga punya segudang pengalaman pahit. Pertengkaran. Dan tangis.
Mulai dari yang sederhana, seperti aku telat menjemputnya di kantor saat jam makan siang. Atau ketika aku tidak menghadiri pesta ulang tahunnya yang ke 22 karena ada meeting mendadak dengan klien.
Atau saat mendengar berita aku dipindahkan ke kantor pusat di Negeri Ratu Elisabeth dan dia meminta untuk ikut kemudian aku berujar bahwa aku belum siap. Sungguh, kata-kata pada waktu itu merupakan penyesalanku yang terbesar. Seandainya aku bisa mengulangi waktu saat itu, aku hanya ingin memundurkan waktu selama 10 menit saja, hanya sampai kata laknat itu tidak meluncur dari bibirku.
“Aku rasa kau sebaiknya pergi.” Aku membuka percakapan kembali.
“Kenapa? Apa karena sinarku membawamu kembali ke masa lalu? Seperti yang biasa kau lakukan?” Ia menoleh kepadaku dan aku menggeleng.
“Bukan. Tapi sepertinya Matahari tak kunjung datang karena kehadiranmu.” Senja tersenyum seraya menjelaskan bahwa memang ia sengaja meminta Matahari keluar sedikit terlambat karena dirinya ingin muncul lebih cepat.
Matahari tentu menolak keinginan Senja. Keluar saat pagi hari? Sungguh gila, pikir Matahari. Namun setelah negoisasi panjang dan Matahari yang tidak tegak melihat Senja begitu memohon, maka ia mengabulkannya.
“Apa alasan kau mau muncul sedini ini?”
“Apa ini?” Senja menunjuk ke arah butiran air yang berada di atas daun pandan.
“Oh, itu embun pagi.”
“Embun?” Aku mengangguk. “Aku tak pernah melihatnya saat kemunculanku.” Ia menambahkan.
“Itu karena ia baru mulai terbentuk pada malam hari.”
“Mengapa demikian?”
“Aku sendiri kurang tau pasti, namun ada campur tangan ketenangan dan dinginnya malam pada proses pembentukannya.”
“Hal yang tidak aku miliki dan itu mungkin kenapa embun tidak pernah muncul.” Senja menatap sendu embun itu. Aku belum pernah melihat Senja semurung ini, mungkin kalau ia yang melihatku murung adalah hal biasa. Tapi kali ini?
“Itu karena sinarmu menghangatkan. Memberi ketenangan dengan cara yang berbeda.” Aku mencoba menangkannya walau ku yakin tidak sebaik caranya menenangkanku.
“Sinar matahari bahkan lebih terang daripada milikku. Ia pun bukan hanya menghangatkan. Tapi kenapa ia diberi kesempatan melihat embun pagi, walau ku yakin hanya sebentar, sedangkan aku tidak?”
“Hmm, tapi ku rasa ada bagian yang Matahari pun tak merasakannya dan ku rasa juga bagian itu sangat penting.”
“Apa itu?”
“Ketika Matahari mulai tenggelam, saat kau sendirian dengan sinarmu, seperti yang kau bilang tadi. Bahwa kau masuk ke tiap jiwa yang menyaksikanmu. Membawa ketenangan. Membawa inspirasi. Membawa harapan. Dan.. Melepaskan kenangan,” aku terdiam sebentar. Senja menunggu. “Kau tahu bahwa lebih banyak puisi dengan menggunakan namamu dibanding Matahari? Begitu pun dengan lagu dan kutipan-kutipan yang ada.”
“Benarkah?”
“Ku yakin begitu. Hey, sudahlah tidak perlu kau murung seperti itu. Tak setiap orang juga punya hal-hal yang sama dengan lainnya.”
“Mungkin kau ada benarnya. Oh ya, dibandingkan yang lain, aku lebih menyukai kejutan.”
“Maksudnya?” Kini aku yang keheranan.
“Kau tahu bahwa aku mengenal miliaran orang di muka bumi ini. Mereka datang kadang untuk hanya sekedar melihatku, sampai yang mencoba melepaskan sesuatu sepertimu,” aku menunjukkan wajah kurang suka dengan kata-katanya, tapi ia melanjutkan. “Kau tahu bagian mana yang aku suka dari semua itu?” Aku menggeleng lemah.
“Yaitu ketika suasana hati mereka yang datang bisa berubah hanya dalam satu malam. Seperti ada yang datang hari ini dengan perasaan sedih, namun ketika esok tiba, ia hadir dengan senyum mengembang dan kebahagiaan. Begitu pula sebaliknya. Dan aku tahu apa yang terjadi pada setelah mereka menunjungiku. Pada saat ini aku merasa bahwa aku merupakan bagian dari mereka. Seperti dirimu. Entah perasaan seperti apa yang sedang dirasakan, mereka selalu mencurahkan sedikit waktunya untuk bercerita denganku; membagi kisahnya dan menertawakan atau menangisinya bersama.”
Untuk beberapa saat aku meresapi kata-katanya. Bahwa ia berkata benar. Aku telah menjadikannya sebagai sahabat tuk mencurahkan isi hatiku. Anggapan bahwa selama ini aku berbicara sendiri ternyata salah, ternyata ia mendengarkan.
“Dan, satu lagi, Al,” dia menatapku lekat. “Seperti yang tadi aku kataan bahwa aku menyukai kejutan, maka aku punya satu untukmu.”
Kejutan? Apa lagi ini?
“Juga tadi aku telah katakan, bahwa aku mengenal miliaran orang. Bahwa bukan hanya dirimu seorang yang mencoba melepaskan beban yang kau pikul dengan bercerita kepadaku.”
“Dan?”
“Dan kau akan segera tahu. Ah, sudah saatnya sekarang. Aku sudah terlalu lama berada di sini, mungkin Matahari sedang mengumpat di sisi lain bumi ini.” Sungguh, kejutan seperti apa yang ia maksud? Ah, tapi aku tak ingin memusingkannya.
“Kau sudah puas?”
“Tentu belum, tapi setidaknya aku tahu seperti apa kehidupan pagi hari. Juga bagaimana bentuk dari embun pagi yang fenomenal itu. Ternyata benar apa yang dibisikkan angin, ini indah, namun sayang sepertinya ini kali terakhir aku melihat mereka. Aku tak akan mencoba menerobos waktu keluarku lagi.” Senja menyelesaikan kata-katanya. Ia perlahan mendekatiku yang sejak tadi tak bergerak dari tempatku, bahkan kopiku belum habis dan sudah dingin. Ia menyentuhku dengan sinarnya. Mencoba menenangkanku seperti biasanya.
Tak lama berselang, ia lenyap. Ia sudah pergi. Seketika muncul sinar baru dari ufuk timur. Sinar yang tepat untuk saat ini, waktu ini. Matahari menampakkan diri. Ia tersenyum ke arahku dan aku mengerti apa maksudnya. Aku membalas senyum itu dan ia segera memposisikan diri lebih tinggi dengan begitu cepat. Mengejar waktu yang telah buang.
Senja telah pergi. Matahari kembali. Embun akan menjadi cerita bagi Senja yang dibawa oleh angin. Membisikannya, menceritakan segala sesuatu yang tak ia ketahui.
Aku masuk kembali ke dalam rumah. Duduk di sofa putih di ruang keluarga. Keluarga? Keluarga siapa? Pikiranku kadang suka kalut jika berada di rumah ini. Tapi kemana lagi aku harus singgah? Rumah ini seperti raga tanpa jiwa. Tampak hidup dari luar, namun mati di dalam.
Kembali aku mengingatnya, dimana aku menolak untuk mempersuntingnya dengan alasan belum siap. Bodoh. Belum siap karena apa? Aku dan dia telah menjadi kekasih selama 4 tahun. Dia merupakan adik tingkatku di kampus dulu, perbedaan umur kami berjarak 3 tahun. Sejujurnya, kami sudah ideal. Hanya aku saja yang tolol.
Semenjak aku bekerja, begitupun dengannya, entah mengapa aku semakin chaos. Tidak bisa mengatur waktuku dengan baik. Tidak bisa mengatur hubungan ini dengan baik. Dan saat perintah harus pindah ke kantor pusat di London, dia, Tisya Aprilia Wijaya, memintaku untuk membawanya sebagai... Seorang istri.
Dan jawaban tolol itu keluar. Aku menolaknya. Saat itu, aku merasa belum siap tapi dia merasa bahwa waktunya tepat. Hingga hubungan kami haru berakhir saat aku baru 2 bulan berada di sana.
Aku bertugas di London selama 2 tahun lamanya dan dalam kurun waktu tersebut aku tidak mencoba menghubunginya. Entah karena aku terlalu kacau, atau aku merasa bodo amat, atau aku memang terlalu disibukkan oleh pekerjaan.
Ketika aku kembali menginjakkan diri di Tanah Air, aku mencoba menemuinya, menghubunginya, mengejarnya dengan penyesalan. Ia menolak dengan alasan sudah memiliki kekasih baru. Sakit? Tentu. Tapi aku bisa apa? Aku yang membuat keadaan menjadi seperti ini. Puncaknya saat aku berpapasan dengannya 2 bulan lalu, di pintu masuk sebuah cafe dibilangan Blok M. Dia keluar dengan seorang pria. Pria yang menggandeng tangannya. Di tangan telah melingkar sebuah cincin di jari manis sebelah kiri. Mereka telah bertunangan.
“Al?” Sungguh, aku lebih berharap ia berpura-pura tidak mengenalku dan terus berjalan menjauh. Bukannya menyapaku seperti itu.
“Hai, Sya.” Kuberikan senyum yang benar-benar kupaksakan.
“Mau ngopi? Sendirian aja?” Iya, Sya, aku sendiran aja. Teman ngopi aku paling asyik sekarang ada di depan aku, tapi digandeng cowok lain. Tentu aku mengucapkan itu di dalam hati. Aku hanya menjawab sampai bagian ‘sendirian aja’.
“Oh iya, kenalin, tunangan aku, Bagas.” Sungguh, aku tak mengerti dengan apa yang ada dipikiran Tisya. Memperkenalkan tunangannya ke mantan kekasih yang masih mengharapkannya? Sya, kamu boleh siksa aku, tapi jangan seperti ini. Sesaat kemudian lelaki metropolitan itu mengulurkan tangannya, menunggu jabatan tanganku. Ingin rasanya aku mengambil pecahan kaca yang ada di belakangku dan menempelkannya pada tangan lelaki itu. Namun pada akhirnya aku menjabatnya dan tersenyum –dengan paksaan tentunya.
“Almer.”
“Bagas,” kurasakan tangannya sedikit erat menjabatku. Kenapa? Dia kesal? Aku rasa sekarang waktu yang tepat untuk mengambil pecahan kaca itu. “Yuk, sayang, kita pulang. Mamah udah nungguin di rumah.” Ia berkata kepada Tisya setelah kami selesai berjabat.
“Yuk,” Tisya mengangguk, “Al, kita duluan ya.” Hanya kubalas dengan senyum. Aku masih mematung di depan pintu masuk. Memerhatikan langkah ringan Tisya menjauh dan... Ia menoleh kembali ke arahku seraya tersenyum. Senyum itu, yang aku rindukan di bawah tarian jingga saat senja, Sya.
Waktu menunjukkan pukul 7.20 WIB. Ternyata percakapan dengan Senja dan lamunanku benar-benar menerobos waktu. Tak heran Matahari buru-buru naik karena memang ia sudah sangat terlambat.
Aku berpikir akan menyalakan televisi, baru saat aku meraih remote-nya. Bel rumah berbunyi. Tamu? Sepagi ini? Jangan bercanda!
Kubawa kakiku dengan malas menuju pintu depan. Bel terus berbunyi. Kesal juga aku mendengarnya, sungguh semakin membuat pagiku rusak.
“Iya sebentar.” Aku raih gagang pintu dan membukanya perlahan.
“Tisya?” Aku mengucek mataku. Memastikan bahwa ini bukan fatamorgana belaka. Ia masih ada di sana. Menatapku dengan... Tunggu, matanya sembab? Dan... Cincin di jari manisnya menghilang?
“Sya.. Kamu kena..” Belum sempat aku menyelesaikan kata-kataku. Ia dengan cepat memelukku. Seketika tangisnya pecah. Air matanya membasahi bahuku. Peluknya. Peluk hangat ini yang aku rindukan. Juga wangi badannya yang tak aku temukan pada wanita lain seakan itu adalah parfum terbaik yang pernah aku cium.
Aku menggerakan tangan menuju punggungnya dengan gemetar. Membelai punggung itu dengan perlahan. Sungguh aku merindukannya. Sya, apapun yang terjadi pada kamu, bahu ini, tangan ini, raga ini, juga hati ini akan selalu ada untukmu, Sya.
Di pagi hari akhir pekan. Setelah pembicaraan dengan Senja. Mungkin, mungkin inilah kejutan yang ia maksud. Sosok yang kurindukan datang dengan keadaan yang membuat hatiku meringis melihatnya. Kemudian ditengah tangisnya ia membisikkan kata-kata ke telingaku,
“Al, maafin aku...”